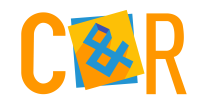Oleh: Zainal Bintang*
Ceknricek.com-Perhelatan Pemilukada serentak pada 27 Juni 2108 menyisakan keanehan yang menghadirkan pertanyaan : wajah demokrasi seperti apa sebenarnya yang sedang dibangun oleh elite politik Indonesia?
Sebutlah salah satunya adalah beredarnya sebuah info grafis di ranah publik yang juga tentunya juga membanjir di media sosial, yakni indeks perolehan suara partai politik hasil quick count.
Partai Golkar menempati tempat paling atas dengan angka kumulatif 59 persen lebih, disusul Nasdem dan Hanura. Selebihnya dalam angka lebih kecil dan di urutan kedua posisi paling buncit PDIP. Perolehan suara partai moncong putih itu sekitar 26 persen.
Dari 171 daerah peserta Pemilukada, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Ada tiga propinsi berpenduduk besar yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Yang menjadi soal, kemenangan yang diperoleh parpol – parpol tersebut kebanyakan berasal dari hasil koalisi. Artinya tidak ada satupun parpol yang memiliki saham mayoritas terhadap satu pasangan calon yang menang itu.
Parpol yang berseteru di tingkat pusat ternyata bisa berkoalisi di level propinsi dan kabupaten kota. Mau tak percaya namun nyata. Di Sulawesi Selatan, misalnya. PDIP bisa berkoalisi dengan PKS yang dikenal sebagai musuh bebuyutan secara ideologi. Permusuhan itu tergambar terang benderang di tingkat pusat.
Bayangkan, ketika kader teras PDIP sedang berjuang keras merambah jalan bagi Jokowi untuk menjadi Presiden pada 2019, pada saat yang sama petinggi PKS secara terang – terangan menggalang kekuatan di masyarakat dengan tagline #2019GANTI PRESIDEN.
Lantas apa yang mempersatukan mereka di tingkat daerah?
Bukankah dengan terjadinya koalisi di daerah terkesan ada penghianatan terhadap garis ideologi yang dibentang pimpinan kedua parpol itu di tingkat nasional?
Publik juga tahu perbedaan ideologi kedua parpol itu sangat tajam. PKS yang dikenal sangat religius bahkan sering dituduh fundamentalis bisa bersekutu dengan PDIP yang relatif sekuler.
Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini dapat dikatakan sebagai pencerminan demokrasi yang sehat? Masih penuh tanda tanya. Yang pasti berdasarkan informasi yang beredar luas di masyarakat, terjadinya tambal sulam koalisi di daerah lebih banyak disebabkan karena faktor pragmatisme.
Dana operasional pimpinan parpol di daerah pukul rata berada dibawah standar kemampuan. Maka mau tidak mau kompromi lewat jalan pragmatis, yakni dengan “menyewakan” perahu bagi paslon yang sanggup membayar angka komitmen tertentu yang tidak kecil jumlahnya.
Fenomena inilah yang menjelaskan, mengapa Nurdin Halid di Sulawesi Selatan (Pilgub) dan Munafri di tingkat kota Makassar mampu memborong hampir semua parpol. Selain bertujuan memberi perkuatan jaringan guna mendulang pemilih, juga mengandung sisi lain yang cukup penting : memotong kompetitor agar mereka ngos ngosan dalam hal membayar mahar parpol pendukung.
Inilah lagu sendu demokrasi Indonesia yang sedang merangkak menapak jalan berliku yang cukup terjal di era reformasi ini. Jika dicermati sejumlah kemenangan parpol koalisi yang digagas parpol pendukung pemerintah (Jokowi), di atas kertas memang menampakkan hasil yang cukup menggembirakan.
Akan tetapi, sekali lagi parpol menengah pengusung Jokowi seperti Golkar, Nasdem dan Hanura, meragukan sebagai jaminan kemulusan Jokowi menuju kursi presiden pada Pilpres 2019.
Keputusan berkoalisi sepertinya didasari dengan semangat gambling yang tinggi alias untung – untungan. Paling tidak ada keuntungan materi yang sangat dibutuhkan di tingkat daerah.
Apa yang dipraktekkan Golkar, Nasdem dan Hanura pada Pemilukada 2018 tidak dapat diandalkan sebagai sandaran kokoh Jokowi.
Sebutlah pasangan Nurdin Abdullah dengan Andi Sudirman Sulaiman yang memperoleh suara terbanyak di Sulawesi Selatan. Tidak ada jaminan kalau itu gambaran murni suara rakyat Sulawesi Selatan. Soalnya PDIP tidk punya akar begitu kuat di Sulsel. Mungkin PKS dan PAN dapat menolong. Tapi tidak ada jaminan.
Sebaliknya, pada kasus kotak kosong pada Pilwalkot Makassar menunjuk kuat itu murni aspirasi masyarakat Bugis Makassar yang marah terhadap diskualifikasi kepada paslon petahana yakni Dani Pomanto, dengan alasan yang kurang diterima akal sehat. Mereka lebih memilih mengisi kotak kosong daripada memilih paslon yang menggunakan berbagai cara yang dinilai kurang terpuji oleh masyarakat Bugis Makassar.
Pada prinsipnya sebagian besar masyarakat Bugis – Makassar masih sangat menjunjung tinggi harga diri dan kehormatan pribadi. Yakni prinsip kepemipinan luhur warisan leluhur : Getteng, Lempu dan Ada Tongeng (Jujur, Tegas dan Satunya Kata dan Perbuatan)
Dari catatan yang diperoleh, terdapat kesimpulan bahwa tersingkirnya calon kuat Golkar Nurdin Halid yang maju dengan dukungan besar sejumlah parpol, maupun Ikhsan Yasin Limpo yang mengandalkan jaringan keluarga besar Yasin Limpo, sangat besar sebagai akibat penolakan dan keengganan rakyat Sulsel kepada figur yang punya kasus hukum dan figur yang terindikasi sebagai bagian dari pelembagaan dinasti.
Termasuk kasus Munafri di kota Makassar. Oleh rakyat Makassar, paslon tersebut hanya disejajarkan dengan kotak kosong.
Celakanya kotak kosong itupun menang, padahal tidak pernah berkampanye. Bahkan tidak ada satupun parpol pendukungnya. Munafri mendapat suara 47,5 persen lebih. Sementara sang kotak kosong yang bertangan kosong itu mendulang suara 52,5 persen lebih. Ini adalah hasil hitung cepat KPU berdasarkan entri model C1 yang dirilis pada hari Jumat (29/06) hari ketiga.
Banyak yang menyebutkan kasus kotak kosong yang menang pada Pilwalkot di Makassar, sekaligus bentuk penghinaan kepada 10 partai politik. Ada gejala masyarakat lambat laun akan melakukan gerakan menolak parpol atau deparpolisasi. Pertanda kekecewaan masyarakat kepada kinerja parpol yang kebanyakan cuma memproduksi koruptor.
Tidak mampu memproduksi regulasi sebagai jembatan emas menuju pulau kesejahteraan sesuai amanat Proklamasi. Artinya kotak kosong itu telah bermutasi menjadi bagian integral dari demokrasi. Menjadi simbol perlawanan rakyat lantaran saluran aspirasinya yang hakiki telah dibajak oleh makelar politik yang mengaku rasul.
*Zainal Bintang, wartawan senior dan anggota dewan pakar Partai Golkar.