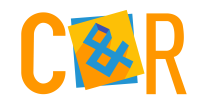Ceknricek.com — Tentang kecintaan terhadap alam, entah diwujudkan dengan naik gunung, pergi ke pantai tersembunyi, atau menelusuri gua-gua dalam tanah, sepertinya kita perlu berkaca pada Soe Hok Gie. Lewat tulisannya, Menaklukan Gunung Slamet, (Zaman Peralihan, 2005; hal 40-41), ia pernah menuliskannya sebagai berikut:
“Kami adalah manusia-manusia yang tidak percaya pada slogan. Patriotisme tidak mungkin tumbuh dari hipokrisi dan slogan. Seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau ia mengenal akan objeknya. Dan mencintai tanah air Indonesia dapat ditumbuhkan dengan mengenal Indonesia bersama rakyatnya dari dekat. Pertumbuhan jiwa yang sehat dari pemuda harus berarti pula pertumbuhan fisik yang sehat. Karena itulah kami naik gunung.”

Ya, bagi Gie, mendaki gunung atau serentetan aktivitas merengkuh alam bukanlah sekadar ikut-ikutan tren atau terlihat keren dengan menyandang ransel sebesar kulkas dan memakai sepatu berhak tinggi tebal yang penuh daki tanah. Baginya, mencintai alam adalah upaya sejenak untuk menghirup udara sebebas-bebasnya ketika melihat iklim politik yang memecah belah rakyat.

Baca Juga: Kisah Hidup Achmad Subardjo, Menteri Luar Negeri Pertama RI
Hingga ia meninggal pada 16 Desember 1969, tepat hari ini, 50 tahun yang lalu, di puncak Semeru akibat menghirup gas beracun jelang sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-27. Ia seolah mengekalkan apa yang telah diucapkan Sophocles, seorang filsuf asal Yunani, bahwa nasib terbaik adalah tidak dilahirkan, yang kedua dilahirkan tapi mati muda, dan tersial adalah umur tua.
Gie dan Indonesia
Soe Hok Gie, lelaki kelahiran Jakarta, 17 Desember 1942, ini dikenal di kalangan pecinta alam sebagai salah satu tokoh panutan dan mahasiswa kritis di zamannya. Bersama teman-temannya ia ikut merobohkan pemerintahan Orde Lama yang belakangan cenderung kian otoriter lewat Demokrasi Terpimpinnya.

“Saya kira saya menyukai Soekarno sebagai seorang manusia, tapi sebagai seorang pemimpin, tidak!,” tulis Gie dalam salah satu catatan hariannya, yang kelak dibukukan menjadi Catatan Seorang Demonstran, (1983). Selain itu, Gie juga dikenal berani dalam menyatakan kritik-kritiknya pada pemerintah di dalam koran.
Setelah lulus dari SMA Kolese Kanisius, Gie melanjutkan kuliah di Fakultas Sastra-Sejarah Universitas Indonesia pada tahun 1962 hingga 1969. Pada saat itu iklim pendidikan di kampus sedang menuju ambang kebobrokan di mana ajang kepentingan politik negara banyak yang menyusup dalam organisasi intra mahasiswa di banyak kampus Indonesia.
Baca Juga: Mengenang Ir Sutami “Menteri Kere” Kesayangan Sukarno dan Suharto

Gie adalah saksi dari pertarungan organisasi ekstra yang bertarung di kampus, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional (GMNI) yang dekat dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), ataupun gerakan-gerakan yang lain.
Menurut Gie, universitas seharusnya menjadi tempat di mana arus pemikiran bergejolak dan tidak boleh dibendung serta diatur oleh intervensi politik maupun pemerintah. Universitas adalah benteng pertahanan terakhir dari sebuah peradaban dan kemerdekaan intelektual.

Berontaklah dia akhirnya, dengan menggelar acara nonton film, musik dan yang lain untuk mempererat silaturahmi antar mahasiswa. Tidak hanya itu, Gie juga mendirikan organisasi mahasiswa pecinta alam (Mapala) pada 12 Desember 1964, yang kelak merujuk juga sebagai nama umum organisasi para pecinta alam di beberapa kampus di Indonesia.
Gie pada waktu itu, mengusulkan untuk membentuk suatu organisasi yang bisa menjadi wadah berkumpulnya berbagai kelompok mahasiswa yang jenuh terhadap intrik dan konflik politik di kalangan mahasiswa. Dalam film Gie (2005) besutan Riri Riza, tergambar bagaimana perdebatan mahasiswa kerap berujung perkelahian, yang menandai runyamnya iklim pendidikan di kampus.

Baca Juga: Museum Prasasti Dalam Lintasan Sejarah
Kini, 50 tahun berlalu setelah Gie mengembuskan nafasnya yang terakhir di puncak Semeru, ia meninggalkan beberapa warisan berharga untuk kita, selain catatan dan prinsip hidupnya dalam bersikap di tengah pragmatisme hidup, hingga ia dimakamkan di Museum Taman Prasasti, Jakarta.
“Tak ada lagi rasa benci pada siapa pun, agama apa pun, ras apa pun, dan bangsa apa pun..dan melupakan perang dan kebencian, dan hanya sibuk dengan pembangunan dunia yang lebih baik,” tulis Gie, di Catatan Seorang Demonstran.
BACA JUGA: Cek SEJARAH, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.