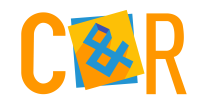Ceknricek.com — Setelah seluruh proses Pemilu 2019 rampung, presiden dan wakilnya telah dilantik, serta merta timbul demam diskursus capres 2024. Sesuai aturan main Jokowi tidak akan maju lagi sebagai capres. Hal itu yang mengundang merebaknya pra “kampanye” parpol untuk memasarkan jagoannya.
Yang paling anyar adalah merebaknya berita hasil Munas X Golkar yang menyebutkan mayoritas DPD peserta meminta kesediaan AH (Airlangga Hartarto) untuk dicalonkan menjadi capres pada Pemilu 2024, sementara itu ada juga peserta yang usul Golkar ke depan mengadakan konvensi capres untuk menjaring calon presiden.
Namun banyak yang pesimis realisasi gagasan hasil konvensi sekalipun, tentunya tidak semudah itu bagi sebuah parpol untuk mendapatkan tiket bagi capresnya. Termasuk, Golkar, sekalipun menggunakan model konvensi untuk mengusung capres sendiri tetap saja mushkil akan berhasil mengusung capres sendiri.
Faktor residu konflik internal yang belum bersih di dalam tubuh partai berlambang beringin itu, yang sewaktu-waktu dapat pecah atas ketidak puasan distribusi kekuasaan internal, dapat muncul di tengah jalan membelah partai itu.
Baca Juga: Dinamika Munas Golkar
Faktor lain ada pula keharusan ambang batas atau PR (presidential threshold) pada pasal UU Pemilu no 7/2017, yang menyebabkan parpol apa pun itu, akan sulit punya calon sendiri tanpa berkoalisi. Ketentuan persyaratan PR (presidential threshold) atau ambang batas pencalonan presiden yang harus dipenuhi jika parpol atau gabungan parpol mau mengajukan pasangan capres berpotensi menjadi batu sandungan.
Pasal (221) tentang calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam (satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pasal (222) yang mengharuskan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, yang harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Persyaratan inilah yang memaksa parpol harus berkoalisi. Ini adalah konsekuensi sistem multipartai ekstrem yang membebani 14 parpol peserta pemilu 2019. Regulasi ini mengharuskan parpol bergabung (koalisi) untuk meraih suara minimal yang dipersyaratkan untuk bisa mengajukan capresnya sendiri. Ini yang disebut simple majority (mayoritas sederhana).
Baca Juga: Akrobat Politik Kader Golkar
Betapapun perkasanya PDIP pada pemilu 2019, meskipun ia punya presiden inkumben plus koalisi dengan beberapa parpol, faktanya tetap saja hanya bisa maksimal kumpul suara kurang lebih 19.33 %. Artinya masih kurang dari 20%.
Di era Orba (Orde Baru) berkuasa dengan top leadernya Soeharto, Golkar memang perkasa dan berjaya. Bisa juara selama enam kali pemilu berturut-turut (1971-1997). Di masa itu dipatok oleh regulasi Orba hanya ada 3 peserta pemilu. Dua parpol yaitu PDI dan PPP serta Golongan Karya, yang tidak mau disebut sebagai parpol, tetapi golongan orang-orang yang berkarya.
Berdasarkan beberapa kajian sejarah dan politik, disebutkan, Soeharto telah melakukan mobilisasi militer dan birokrasi untuk menopang ketangguhan Golkar melalui doktrin tiga jalur (ABG – ABRI, Birokrasi dan Golkar).
Praktik itu disebut mobilisasi vertikal yang bersifat “komando”. Hal itu dimungkinkan karena posisi Soeharto yang strong leader sebagai presiden memiliki kekuasaan politik multidimensi: menjadi pemimpin “koalisi semu” yang powerfull yaitu tiga jalur ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar).
Mobilisasi vertikal itu membuat Golkar selalu menang mutlak, meraih suara terbanyak selama enam kali pemilu yang bervariasi antara 64 % – 75% setiap pemilu. Ini yang disebut single majority (mayoritas tunggal).
Pada era Orba kendali negara ada di tangan Golkar yang “berhasil” melestarikan kader Golkar Soeharto sebagai presiden selama 32 tahun. Selalu menang dari pemilu ke pemilu tanpa pesaing. Yang kesemuanya itu dimungkinkan oleh faktor mayoritas tunggal hasil “rekayasa genetik” kekuasaan Orba.
Baca Juga: Jabatan Presiden RI 3 Periode?
Terkait dengan paparan fakta faktual tersebut di atas, maka parpol yang hendak mengusung sendiri capresnya pada Pemilu 2024, termasuk Golkar tentunya, maka fraksi-fraksi mereka di parlemen harus pro aktif membangun kesepakatan mengubah atau merevisi UU Pemilu yang tidak bebas hambatan, menjadi pemilu bebas hambatan.
Banyak kajian menyebutkan keberadaan UU pemilu tersebut sangat complicated, dan merepotkan, baik penyelenggara, parpol peserta maupun masyarakat pemilih.
Banyak yang menyamakannya sebagai “hantu” demokrasi dikarenakan sistem itu menelan biaya besar, menyita waktu dan energi bangsa, merenggut nyawa rakyat serta membelah persatuan.
Mungkinkah akan ada kesepakatan para parpol untuk merevisi UU Pemilu? Sementara UU itu ditengarai oleh publik telah “diblok” oleh kekuatan oligarkis hasil kolaborasi aktor politik dan investor ekonomi.
Soalnya, mereka–para oligarkis itu–sudah merasa nyaman dengan kondisi “semi” anomali regulasi pemilu saat ini, yang membuat tidak satu pun parpol bisa leluasa merevisi sejumlah regulasi yang berbau: “dari oligarkis untuk oligarkis”.
Jangan-jangan dedengkot oligarkis yang berjubah politisi itu justru sedang gentayangan disekitar kita sebagai “hantu” demokrasi?
Wallahu a’lam bishawab!!
*Zainal Bintang, wartawan senior dan pemerhati sosial budaya.
BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini