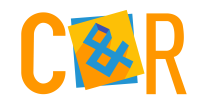Ceknricek.com — Minggu pertama tahun politik 2024 berjalan dengan kondisi tidak sedang baik – baik saja. Kompleksitas masalah pemilu, dari dampak adanya indikasi pemilu curang semakin mengemuka. Hiruk – pikuk proses tahapan pemilu sudah sarat (ditandai) dengan berbagai protes atau laporan/pengaduan ke tiga tim Paslon ke Bawaslu.
Memang, patut disayangkan, karena tampaknya pemilu ini tidak disertai dengan kontestasi gagasan atau dialektika pertukaran ide – ide besar untuk sebuah capaian kemajuan demokrasi. Padahal, masa depan republik ini harus diakui bahwa suka atau tidak sedang dalam pertarungan besar, untuk memperkuat nilai – nilai tatanan kehidupan bernegara dari keseluruhan sistem dan aturan sebagai hasil produk reformasi. Bukan sebaliknya dihambat dengan kekerdilan jiwa pemimpinnya sendiri seperti yang telah dirisaukan Mohammad Hatta dalam Demokrasi Kita (1960).
Oleh sebab itu, untuk menjadi republik ini sebagai bangsa modern yang besar sebagai wujud harapan pendirinya (founding fathers). Maka, mau tak mau Indonesia harus dipimpin oleh pemimpin besar dengan pikiran besar demi kebesaran bangsanya. Pemimpin besar itu harus secara totalitas menjiwai kesadaran tentang arah bangsa ke depan dengan berkata jujur bahwa kita sedang mengalami berbagai tantangan dalam menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial untuk rakyat. Karena itu, kita harus menghadapi dengan “menancapkan” yang kuat modal sosial, berupa kepercayaan publik (public trust).
Dalam konteks ini, dukungan warga masyarakat untuk mau secara bersama – sama bergandengan tangan membangun bangsa ini ke depan sangat diharapkan. Tentu bukan dukungan semu, pemaksaan melalui intimidasi, sehingga membuat pemilu tidak berkualitas (bermartabat). Sebab, yang ada dalam praktek rakyat sebagai prinsip dasar demokrasi menjadi “terpasung”. Akibatnya yang terjadi mencuat ke permukaan adalah fenomena potret buram pemilu jurdil. Kenyataannya, makin berjarak antara apa yang seharusnya (das sein) dengan realitas yang ada di masyarakat (das sollen).
Demokrasi yang lumpuh
Indikasi kuat terjadinya penurunan kualitas demokrasi yang sangat tragis ini, merupakan dampak buruk dari “libidio” kekuasaan untuk memimpin dengan cara mendominasi seluruh aspek kehidupan publik yang ada dalam genggaman dengan cara “cawe-cawe kekuasaan”.
Tentu saja, dengan perhitungan dan asumsi dasar pemikiran bahwa seluruh instrumen kekuasaan yang ia miliki, masih efektif di operasionalkan. Artinya, pemerintah yang masih tersisa masa jabatannya dengan leluasa akan menekan kepada institusi yang dianggap strategis untuk penyelenggaraan pemilu. Atau dengan kata lain, pemerintah dengan kekuasaan yang ia pegang masih potensial menggerogoti kekuasaan dominatifnya untuk melakukan intervensi.
Dominasi yang jadi syahwat pemerintah menjadi kuasa tunggal atau terbesar segala hal Ikhwal urusan. Ingatlah bagaimana pemerintahan orde baru bisa mencapai kekuasaan selama 32 tahun, tentu tak lepas karena memanfaatkan institusi negara dan fasilitas sumber daya penyelenggaraan pemilu.
Intinya, dengan menggunakan fasilitas, sumber daya yang melimpah, jaringan birokrasi sampai ke daerah / desa, serta dana bantuan sosial BLT dll. Walaupun apa yang dibantukan itu seringkali masih ada klaim pemerintah, padahal sesungguhnya adalah milik atau hak rakyat itu sendiri. Peruntukannya kepada kesejahteraan rakyat atau untuk kebahagiaan rakyat pribadi. Jadi bukan bersumber dari uang pribadi pemerintah, apalagi bersumber dari salah satu Paslon.
Hal itu, perlu diketahui bersama agar seluruh gerak gerik pemerintah sekarang (presiden) tidak mudah dipolitisir atau disalah artikan. Maka, seluruh inci kehidupan bernegara haruslah merujuk pada prinsip – prinsip real demokrasi, tidak boleh masuk ke wilayah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang pada gilirannya membuat demokrasi jadi lumpuh.
Rakyat sebagai potret negara
Karena itu, berbagai catatan yang mengkhawatirkan itu, bisa diatasi dengan mengembalikan rakyat sebagai pengarusutamaan potret bernegara. Dan, pemilihan umum merupakan realisasi kehendak rakyat, artinya pemilu sebagai instrumen untuk memastikan adanya sirkulasi kekuasaan secara demokratis. Hal itu secara jelas dan tegas melalui konstruksi UU No 7 tahun 2017 Tentang Pemilu yang menegaskan pemilu serentak untuk memilih pejabat eksekutif dan legislatif.
Dengan pengentalan pemahaman demikian, paling tidak kegelisahan kita terhadap terjadinya “chaos” mendorong perasaan jadi cair dan dinamis menanggapi perbedaan yang ada. Kita makin mafhum dan dewasa mengelola sekat – sekat yang ada, sehingga perspektif emosional yang tersebar dapat diantisipasi dengan kearifan yang ada.
Sekali lagi, meski beragam kepentingan, serba stereotip, dan rawan konflik. Namun, akhir cerita senantiasa dipenuhi term, jargon, narasi sejuk, serta pesan moral, dan sinopsis spiritual formula ” happy ending ” yang damai.
Akhirnya, betapapun situasi sosial budaya masyarakat dikhawatirkan memicu ketegangan yang pada gilirannya menimbulkan setting konflik sosial yang dahsyat. Akan tetapi , hal ini dapat terelakkan dengan mengurai masalah dengan kearifan – kearifan lokal untuk memperkuat modal sosial sebagai refleksi peradaban masyarakat. Serta budaya rembuk bersama dalam memecahkan sumber-sumber konflik sebagai poros utama kultur ala Indonesia. Kesemuanya ini, diharapkan mampu menjadi pilar dan sumber inspirasi pemecahan berbagai ketidakpuasan para pendukung kandidat Capres/Cawapres di puncak menuju pemilu atau pasca pemilu 2024.
Jakarta, 7 Januari 2024
#Abustan, Pengajar S2 Universitas Islam Jakarta (UID)