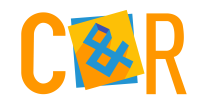Ceknricek.com–‘’Mas, saya sudah membaca tulisan Anda, saya kira Dudung Kece siapa, karena menurut saya Letjen Dudung ga kece-kece amat hehehe…tapi inti curhat Anda bisa saya pahami dan saya terima.’’
‘’Waduh..mohon maaf Gus, saya sungguh tersanjung panjenengan membaca tulisan saya dan memahaminya, sungguh suatu yang tak terbayangkan bagi saya wong cilik ini…Tapi, ada hal yang masih amat mengganjal di benak saya Gus, berkenankah Gus Dur yang mulia dan sebagai Bapak Bangsa memberi pencerahan bagi saya dan seru sekalian anak bangsa tentang curhat saya tersebut: apa yang seyogyanya kita lakukan demi membendung arus hoax dan saling sengkarut dalam keberagaman kita dewasa ini?’’
‘’Walaaah..gitu aja koq repot tho..katanya Anda akademisi, Pak Jaya Suprana banyak cerita kepada saya, lhaa koq tidak tahu bila Harvard Business Review belum lama ini memuat hasil kajian yang dijalankan oleh The Fletcher School di Universitas Tufts bertajuk Digital Trust around the World? Atau, bila dirunut ke belakang, tahun-tahun sebelumnya juga telah banyak dilakukan kajian terkait digital trust (kepercayaan digital) ini, baik oleh lembaga-lembaga nirlaba maupun beragam institusi berorientasi profit. Intinya sebenarnya kan sederhana saja Mas: digital itu berarti segala sesuatu penyimpanan informasi dinyatakan dalam binary digit yaitu nol atau satu, wis gitu aja, tapi dalam kesederhaan itulah seluruh dunia kemudian bisa dijangkau dan dirangkul sedemikian dahsyat hingga seperti saat ini.
Berbagai kajian kelas dunia tersebut sampai pada simpulan bahwa digital trust itu mencakup tiga pilar utama yaitu teknologi, proses, dan manusia. Sebagaimana saya duga sebelumnya, diantara ketiga pilar tersebut, manusia (people) adalah garda depan dan pemeran utama!
Jadi, bila bangsa Indonesia bertekad dan berkehendak sungguh menumbuh-kembangkan digital trust bagi kemashalatan seluruh negeri, bukan basa-basi belaka, mau tidak mau ya mesti meningkatkan kualitas insani secara total-menyeluruh-dan sinambung alias konsisten, tidak mencla-mencle, melompat sana melompat sini atau sekedar tambal-sulam. Gitu aja koq repot…’’
‘’Sebentar..sebelum Anda menyela, saya tambahkan dulu penjelasan saya ya…nah bila kita bicara tentang pengembangan sumber daya insani, maka akar masalah kembali kepada edukasi, tiada yang lain. Hal ini terjawab dalam dua hipotesis Michiko Kakutani, pertama, sistem pendidikan lemah adanya bukan hanya dalam pembelajaran keterampilan dasar tetapi juga logika yang melandasi berbagai keterampilan tersebut.
Kedua, karena makin kuatnya gelombang radikalisme agama (dengan tidak merujuk pada agama tertentu lhoo, tetapi bersifat generik, bisa agama apa saja).
Dalam konteks Indonesia kini, kiranya kedua hipotesis tersebut bercumbu mesra, berjalin berkelindan dibuai angin sorga demokratisasi pasca reformasi serta ditingkahi semerbak wangi bebasnya media sosial seolah tanpa kendali. Tiap upaya melakukan kendali atasnya selalu digugat dalam wacana ‘membungkam ekspresi dan demokrasi’, pada titik inilah pemegang otoritas perlu memainkan rem dan gas secara bijak seperti proses pengendalian pandemi Covid-19 itu lhoo..mem-balance antara kesehatan dan ekonomi.
Higher order thinking skills yang seharusnya menjadi arus utama pembelajaran dan pendidikan malah terpinggirkan, menjadi tandus dan berjamur kerak hingga mati lunglai. Praktik dan praksis pendidikan macam inilah, menurut tesis Kakutani di atas, justru menjadi arena pembiak nan efektif bagi mekarnya radikalisme dan fanatisme sempit atas nama apapun: agama/keyakinan, ideologi, identitas, dan sebagainya.
Dengan kata lain, tak berlebihan kiranya bila dunia pendidikan kita tak bisa berdiam diri belaka dan mesti terpanggil menggelorakan arus balik melawan kabut tebal post-truth dengan segala manifestasi kedangkalan berpikirnya yang amat penuh risiko.
Pertama, dia amat berpotensi merusak proses pendidikan karakter yang digaungkan selama ini. Bila potensi risiko ini tidak segera dikelola, maka akan merembet pada potensi risiko kedua yakni kecenderungan makin maraknya tren pencitraan dan mengukuhkan kebohongan serta menabalkan keluhuran otentisitas-kreativitas.
Selanjutnya, ketiga, makin jauhnya kita pada etos verifikasi fakta dan makin cenderung menerima segala yang sesuai-seirama dengan ‘ke-aku-an’ ideologis, religius, politis, dan ‘aku-aku’ lainnya serta menafikan keberagaman; dan pada akhirnya model pembelajaran yang bersifat indokrinatif serta tertutup akan dialektika perbedaan makin menumbuh-suburkan kebencian akan para liyan serta menumpulkan kepekaan solidaritas komunal yang beragam.
Inilah akar masalah (root cause) yang mesti kita benahi bersama, termasuk sampeyan yang katanya mengajar di beberapa perguruan tinggi atau para ulama yang mengampu puluhan ribu pesantren di seluruh pelosok Nusantara. Kita mesti bahu-membahu, seluruh komponen bangsa mesti bertanggung-jawab dan terlibat..janganlah semua ditimpakan pada Mas Menteri..kasihan lhoo dia itu..Wis yoo..saya rehat dulu..’’
‘’Inggih Gus, matur sembah nuwun…banyak terima kasih Gus dhawuh-nya…moga berkenan kita lanjut nanti..’’
*)Greg Teguh Santoso, akademisi dan pemikir bebas