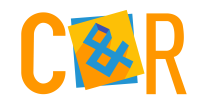Ceknricek.com — Elemen masyarakat sipil telah beberapa kali mencoba membuat Laporan Kepolisian (LP) terhadap Presiden Jokowi ke Bareskrim Polri terkait kerumunan massa. Namun sampai sekarang laporan tersebut tidak diterima, atau tidak diproses oleh pihak kepolisian tanpa alasan hukum yang jelas. Akibatnya, penolakan tersebut menjadi amunisi jitu untuk mendegradasikan konsep “Polri Presisi” yang diusung Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang mencitakan polri prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
Pengaturan Hak Membuat Laporan Kepolisian
Era 4.0 yang telah menggeser aktifitas manusia dari pikiran dan perilaku faktual menjadi virtual atau maya memang telah menjebak masyarakat awam ke dalam pikiran dan perilaku tanpa pola (disrupted) yang memunculkan asumsi umum bahwa semua tindakan boleh dilakukan atau semua informasi dapat di-share, hanya berdasarkan pikiran atau pertimbangan personal atau kelompok yang sering kali superfisial bahan bohong. Seiring dengan itu, muncul pula profesi pendengung tengik (hoaxer buzzer) yang pekerjaannya menyebarluaskan informasi sampah demi menerima bayaran.
Dampaknya, menurut hasil survei terbaru Microsoft, Indek Peradaban Digital (Digital Civility Index) neziten Indonesia paling buruk di Asia Tengara. Netizen Indonesia dikenal sebagai netizen paling paling tidak sopan. Dimensi inilah yang mestinya menjadi pemicu pembahasan komprehensif tentang tindak pidana siber yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11 Tahun 2008 yang diubah dengan UU 19 Tahun 2016.
Era disrupsi informasi tentu mampu menafikan esensi kehidupan bermasyarakat apalagi bernegara yang secara absolut mensyaratkan adanya mekanisme dan kelembagaan sebagai pola perilaku teratur yang dibingkai dalam aturan hukum. Oleh karena itulah hukum besi kehidupan manusia yang dalam premis klasik ilmu hukum dikenal dengan adagium ubi societas ibi ius (di mana ada masyarakat di situ ada hukum-red).
Secara yuridis normatif Pasal 108 UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sejatinya telah mengatur hak atau kewajiban warganegara untuk membuat LP baik lisan atau tertulis. Menurut norma Pasal 108 KUHAP, ada 3 kategori pelapor tindak pidana, yaitu;
(1). Saksi atau saksi korban tindak pidana apapun, (2). Setiap orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, dan (3).Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui terjadinya tindak pidana.
Secara tekstual memang norma Pasal 108 KUHAP mengagregasi seolah semua orang dapat membuat laporan kepolisian. Padahal secara substantif legalistik sejatinya tidak demikian. Oleh karena ada pembatasan atau pengecualian baik berdasarkan norma delik yang diatur dalam UU, atau norma putusan Mahkamah Konstitusi.
Pengaturan atau pembatasan terhadap hak membuat LP seharusnya diatur secara baik dan tepat, baik dalam level UU, Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana UU, atau dalam Peraturan Kapolri (Perkap) sebagai aturan teknis prosedural.
Pada level praksis memang Kapolri telah mencoba mengatur hak membuat LP melalui Peraturan Kapolri (Perkap) No. 6 Tahun 2019 sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Perkap tersebut. Namun dalam dimensi ilmu perundang-undangan, materi muatan Pasal 3 Perkap tersebut, bukan saja tidak lengkap dan terlalu sederhana; lebih dari itu tidak mengatur adanya pengecualian hak membuat LP berdasarkan jenis delik yang diatur dalam UUD 1945, UU atau putusan Mahkamah Konstitusi.
Dalam praktiknya, pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Perkap No.6 Tahun 2019 sering kali menimbulkan kesulitan bagi warga negara yang hendak membuat LP. Terutama ketika petugas penerima LP cenderung mengharuskan pelapor untuk menyertakan bukti surat atau dokumen sebagai bahan kajian awal. Praktik demikian secara dimensial melanggar ketentuan Pasal 184 KUHAP yang secara jelas mengatur bukti perkara pidana bukan cuma berupa surat, melainkan ada bukti lain berupa saksi, ahli, petunjuk atau pengakuan.
Oleh karena itu, senyatanya terdapat urgensi hukum agar Kapolri segera merevisi dan melengkapi norma Perkap No.1 Tahun 2019 agar tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dalam membuat LP, sebaliknya guna membangun kinerja dan citra positif “Polri Presisi”.
Hak Melapor Presiden
Salah satu materi muatan hukum (legal matter) yang harus diatur baik dalam UU Lembaga Kepresidenan, atau secara teknis dalam Perkap adalah hak melapor Presiden dan/atau Wakil Presiden. Oleh karena senyatanya terdapat kekosongan hukum, sebab sampai sekarang belum ada norma hukum positif yang mengaturnya secara baik, tepat dan lengkap.
Secara konstitusional, UUD 1945 mengatur bahwa pribadi warganegara yang menjabat sebagai Presiden dan/atau Wapres mengalami proses impersonifikasi. Artinya pribadi tersebut melebur ke dalam jabatan selama dia menjabat. Ajaran atau teori impersonifikasi bukan hanya dianut oleh UUD 1945, melainkan juga konstitusi Amerika Serikat.
Atas dasar ajaran impersoninfikasi inilah Donald D Trump tidak dapat diproses menurut hukum pidana meskipun dia terlibat kasus domestic terror Capitol Hill. Sebab, ketika kasus itu terjadi, Trump masih menjabat sebagai Presiden Amerika. Tuntutan hukum yang mungkin dikenakan terhadap Trump hanyalah pemakzulan (impeachment).
Ajaran impersonifikasi melahirkan impunitas hukum yang menyebabkan yang pribadi yang memangku jabatan Presiden dan/atau Wapres tidak dapat dituntut secara hukum sebab berada dalam kedudukan “beyond the reach of judiciary process” yang di Amerika disebut “The Presidential immunity from judiciary direction.” Dalam kedudukan demikian, Presiden Amerika sebagai kepala pemerintahan, tidak boleh diadili dalam proses pidana, tapi boleh dikalahkan melalui proses politik (political struggle) (Bahrul Ilmi Yakup, Kompas, 27/11/2013).
Meskipun tidak setegas konstitusi Amerika, UUD 1945 juga menganut ajaran impersonifikasi yang menyebabkan Presiden dan/atau Wapres Indonesia tidak dapat dituntut dalam proses pidana selama menjabat. Aturan demikian dapat dibaca dan dipahami dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur Presiden sebagai kepala pemerintahan dan Pasal 7 UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan Wapres Indonesia memiliki masa jabatan tetap selama lima tahun.
Oleh karena itu, UUD 1945 tidak mengatur proses pemidanaan terhadap Presiden atau Wapres, melainkan menggeser dan menjadikan tindak pidana yang dilakukan Presiden atau Wapres menjadi alasan pemakzulan dalam yurisdiksi proses politik sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Dengan demikian, secara substansial, UUD 1945 memang mengecualikan Laporan Kepolisian terhadap Presiden dan/atau Wapres Indonesia. Kedudukan Presiden sebagai lembaga menjadi alasan konstitusional untuk menyampingkan asas persamaan di depan hukum (equality before the law).