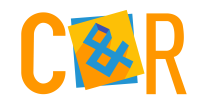Pro dan kontra usulan penundaan pemilu membuat beberapa pakar mencoba menganalisisnya dari sisi akademi dan politis. Salah satunya dari Yusril Ihza Mahendra. Berikut tulisan panjangnya yang dibagi dalam lima (5) bagian:
Jalan kedua, di luar mengubah UUD 45 adalah Presiden mengeluarkan Dekrit menunda pelaksanaan pemilu dan sekaligus memperpanjang masa jabatan semua pejabat yang menurut UUD 45 harus diisi dengan pemilu.
Dekrit adalah sebuah revolusi hukum, yang keabsahannya harus dilihat secara post-factum.
Revolusi yang berhasil dan mendapat dukungan mayoritas rakyat, kata Professor Ivor Jennings, menciptakan hukum yang sah. Tetapi sebaliknya revolusi yang gagal, menyebabkan tindakan revolusi hukum sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Pelaku revolusi yang gagal bisa diadili oleh pengadilan dengan dakwaan makar (kudeta) atau pengkhianatan terhadap bangsa dan negara, atau dipecat dari jabatannya oleh lembaga yang berwenang.
Masalahnya apakah Presiden Jokowi punya nyali untuk mengeluarkan dekrit, sebagaimana Bung Karno mengeluarkan Dekrit membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 45?
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu bukanlah tindakan yang didasarkan kepada dalil “staatsnoodrechts” (keadaan darurat negara) atau “noodstaatsrechts” (hukum tata negara dalam keadaan darurat) sebagaimana didalilkan oleh Prof. Mr Djokosutono dan Prof. Mr. Notonegoro karena tidak cukup alasan untuk menyatakan adanya faktor itu.
Dekrit 5 Juli 1959 adalah sebuah revolusi hukum yang berhasil berkat politik cipta kondisi yang kala itu diorganisir oleh Kepala Staf Angkatan Perang Jenderal AH Nasution yang lebih dulu menyatakan SOB (Staat van Oorlog en Beleg) atau “negara dalam keadaan bahaya”, serta dukungan partai-partai politik terutama PNI dan PKI. Revolusi hukum tidak mungkin akan berhasil tanpa dukungan militer. Itu sejarah tahun 1959.
Presiden Gus Dur juga pernah mencoba melakukan revolusi hukum dengan mengeluarkan dekrit membubarkan DPR dan MPR hasil Pemilu 1999. Sebelum niat itu dilaksanakan, saya sudah memberikan tausiyah kepada Presiden Gus Dur resmi dalam sidang kabinet tanggal 6 Februari 2001. Saya mengingatkan Presiden dalam posisi saya sebagai Menteri Kehakiman dan HAM yang memang berkewajiban memberikan nasehat hukum kepada Presiden.
Saya katakan bahwa rencana Presiden mengeluarkan maklumat atau dekrit membubarkan DPR dan MPR itu adalah tindakan inkonstitusional yang sangat berisiko. Kalau tindakan itu mau disamakan dengan tindakan Bung Karno tanggal 5 Juli 1959, maka landasan sosiologis, politis dan konstitusional untuk itu tidak ada. Lagipula dekrit hanya akan berhasil jika didukung oleh kekuatan militer. Sementara saya melihat TNI kala itu justru enggan mendukung langkah inkonstitusional tersebut. Mengingat pada waktu itu DPR sudah mengeluarkan memorandum I kepada Presiden, saya menyarankan agar Presiden mengundurkan diri saja. Hal itu baik bagi Presiden pribadi, dan baik juga bagi bangsa dan negara daripada Presiden dipermalukan dengan diberhentikan oleh MPR.
Namun tausiyah saya itu disambut Presiden dengan kemarahan. Esoknya tanggal 7 Februari 2001, saya diberhentikan sebagai Menteri Kehakiman dan HAM dan digantikan oleh Baharudin Lopa. Lopa bersedia mewakili Presiden menjawab memorandum I dan II di MPR, suatu tugas yang sebelumnya saya tolak untuk melaksanakannya. Dekrit akhirnya diteken oleh Presiden Gus Dur tanggal 23 Juli 2001 yang mendapat dukungan begitu banyak dari kalangan aktivis, akademisi dan tokoh-tokoh LSM yang berbondong-bondong datang ke Istana. Namun karena sebagai sebuah tindakan revolusi hukum yang tidak matang, MPR segera bersidang dan menjawab dekrit Presiden sebagai pelanggaran terhadap konstitusi dan haluan negara. Maka, Presiden Gus Dur diberhentikan dari jabatannya.