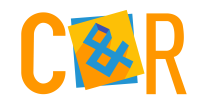Ceknricek.com–Korupsi nampaknya sudah melekat pada kita. Bukan sekarang saja, melainkan juga sudah sejak lama.
Pernah Wakil Presiden pertama NKRI Mohammad Hatta memperingatkan “agar jangan sampai korupsi menjadi budaya di Indonesia”. Peringatan itu kemudian ditanggapi pimpinan koran Indonesia Raya (waktu itu) Mochtar Lubis, dengan sentilan, “kalau sudah membudaya maka diajarkan saja di sekolah.”
Nyatanya korupsi memang tidak mampu diberantas, dan kini malahan merajalela di Indonesia, meski tidak sampai diajarkan di sekolah. Namun revisi UUD KPK mungkin berdampak mudharat terhadap pemberantasan korupsi.
Ketika kasus korupsi yang ditengarai akhirnya akan menggemparkan banyak orang sewaktu terbongkar baru-baru ini yang melibatkan salah seorang pejabat tinggi di Direktorat Pajak, pimpinan bangsa ternyata, secara sengaja atau tidak, hanya berpesan agar “jangan hedonis” alias jangan pamer.
Pesan itu sayangnya mudah ditafsirkan sebagai ungkapan: “Mau korupsi silahkan saja, tapi hasil korupsi jangan dipamerkan kepada masyarakat”.
Patut dikhawatirkan bahwa kalau korupsi memang sampai berjangkit laksana penyakit menular di kalangan mereka yang memang punya peluang untuk itu di Indonesia, maka celakalah kita. Karena perbuatan durjana itu akan dianggap sebagai suatu keharusan, semacam fait accompli.
Mungkin saja belakangan ini seorang pejabat yang berada dalam keadaan di mana dia bisa korupsi namun tidak melakukannya akan dianggap tolol.
Saya pernah mendengar dari seorang sahabat karib pejabat yang waktu itu menjadi pimpinan Direktorat Pajak, Mar’ie Muhammad. Sahabat saya dan pimpinan Direktorat Pajak itu setiap akhir pekan melakukan jalan sehat bersama sekitar Gelora Bung Karno.
“Suatu ketika,” begitu dia bercerita,”Saya punya masalah pajak. Maklum saya kan pengusaha. Jadi saya sampaikan kepada sahabat saya itu. Dan Mar’ie mengatakan, agar hari Senin saya singgah di kantornya.”
Kata sahabat pimpinan Direktorat Pajak itu, ketika ia sampai di kantor Mar’ie Muhammad, sahabatnya itu memanggil seorang petugas bagian penyuluhan Direktorat Pajak, dan menyuruhnya membawa “tamunya” itu ke sebuah bagian lain di Direktorat Pajak.
“Wah saya dibawa ke sebuah tempat penyuluhan pajak dan hampir seharian saya ‘dicekoki’ kewajiban harus membayar pajak sebagai seorang warganegara yang baik,” kata sahabat saya itu.
Kapok!
Pada hal dia bersahabat dengan sang pimpinan Direktorat Pajak! Sayang orang sejujur Mar’ie Muhammad kurang sering diingat. Jangan-jangan ada yang menganggapnya “tolol”!
Ada riwayat yang mengatakan bahwa ketika ia akhirnya diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi Menteri Perdagangan, ia menyampaikan kepada keluarganya, agar mereka hidup lebih hemat lagi.
Loh kok?
“Sebagai pegawai,” katanya kepada keluarganya, “Saya bisa nyambi kasih kuliah di sana sini hingga penghasilan kita bertambah. Namun sebagai menteri itu tidak lagi mungkin dilakukan.”
Waktu itu , beredar desas desus bahwa Presiden Suharto tidak berani memecatnya sebagai menteri karena ada ancaman dari Bank Dunia. Allahu a’lam.
Kalau judul tulisan ini menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia “lain dulu lain sekarang”, memang itu ada alasannya.
Memang dahulu di kampung halaman saya (Medan) kalau ada seorang remaja naik motor (yang harganya waktu itu dianggap sangat mahal) dan mampu beli kemeja merk “Arrow” atau “Crocodile”, maka orang akan berkata: “Tidak heranlah, ‘kan bapaknya kerja di kantor belasting!”
Dahulu di Medan memang orang lebih suka menggunakan kata belasting karena pajak bisa berarti pasar tempat orang berjual-beli. Lagi pula di zaman itu uang yang dimiliki negara tidaklah sebanyak seperti sekarang ini. Tapi ada satu hal yang menarik di zaman itu yang mencerminkan bahwa bagaimanapun yang korupsi waktu itu masih punya rasa malu.
Seseorang yang korupsi kalau hendak menghamburkan hasil perbuatan durjana nya itu akan mencoba kasak kusuk mencari orang yang tiket loterenya memenangkan hadiah pertama “satu juta rupiah” – jumlah uang yang sangat besar waktu itu.
Dahulu tiket lotere biasanya dijual di kaki lima jalan oleh orang Tionghoa yang kelihatannya memang uzur-uzur. Hadiah pertamanya satu juta rupiah. Nah, seseorang yang beruntung memenangkan hadiah pertama, biasanya tidak langsung menguangkan tiketnya itu, melainkan mencari pejabat yang korup yang biasanya berani membeli tiket itu dengan harga lebih dari satu juta rupiah.
Pejabat tersebut kemudian akan menghubungi sejumlah wartawan lokal untuk menyampaikan nasib baiknya itu. Berita bahwa pejabat tadi telah menang lotere niscaya akan diketahui setiap pembaca koran yang waktu itu hanya terdiri dari empat halaman.
Pejabat tadi bisa saja menghamburkan sepuluh kali lipat dari jumlah yang dimenangkannya dalam undian lotere itu, dan masyarakat tidak akan menyadarinya. Mereka hanya akan mengatakan, “Iyalah ‘kan dia menang lotre satu juta rupiah.” Meski dia menghabiskan lima juta. Tidak akan ada yang menghitung setiap pengeluaran yang dilakukannya. Bagaimana pun pejabat seperti itu masih punya malu, meski perbuatannya tetap durjana.
Dalam tahun 1954 penggubah lagu Indonesia yang sangat luar biasa, Ismail Marzuki, menciptakan lagu “Minal Aidin Wal Faizin” yang kemudian menjadi sangat populer khusus edisi yang dinyanyikan Didi.
Payah dipercaya bahwa dalam bait terakhir lirik lagu tersebut, Ismail Marzuki menyampaikan pesan yang sampai sekarang masih selaras, bahkan lebih selaras:
Maafkan lahir dan batin,
‘lang taon hidup prihatin
Kondangan boleh kurangin,
Korupsi jangan kerjain
Jadi bukan saja peringatan “jangan hedonis, jangan pamer, melainkan JANGAN KERJAIN!” Begitu.