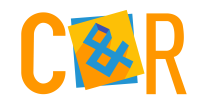Ceknricek.com — Dalam kritik film, yang harus dinilai adalah bahasa film. Bahasa gambar. Sebaliknnya, sejak awal kemunculanya, kritik film di Indonesia lebih menyerupai “kritik sastra” ketimbang kritik film. Walhasil, jadilah kritik film, tapi rasa sastra.
Para penulis kritik film, sebagaimana layaknya kritik sastra, lebih banyak “membedah” aspek cerita berikut detail-detailnya. Kalau pun para “kritikus film” membicarakan karakter pemain, yang disorot karakter layaknya di dunia sastra. Demikian pula, kalau membahas soal plot, yang dikupas seperti plot dalam naskah-naskah sastra. Dengan demikian, tidak mengherankan, walaupun bernama kritik film, namun sifatnya tak jauh berbeda dengan kritik sastra.
Dalam karya sastra , pelukisan dapat diuraikan dengan kata-kata. Sastrawan mengekspresikan karyanya kepada pembaca dengan menangkap pengertian yang tertulis. Berbeda dengan film. Segalanya harus dilukiskan melalui gambar hidup, ditambah unsur penunjang musik dan sudut pengambilan kamera, editing dan sebagainya. Penonton harus diajak memahami persoalan melalui adegan demi adegan di layar. Kendati ada dialog sebagai faktor penunjang, faktor utama tetap gambar hidupnya. Tak dapat hanya dilukiskan “saya kesepian,” atau “dia sedang diliputi kerinduan.”
Tidak heran ada pengamat film ketika mengupas film Indonesia Abracadabra, misalnya, mengatakan dia tidak suka film karya sutradara Fozan Rizal ini, karena sejak pertengahan film si “pengamat” mengharapkan cerita mengerucut pada kejelasan atau fokus urusan keluarga, tapi karena hal itu sama sekali tidak terjadi di film Abracadabra, filmnya bagi si pengamat menjadi tidak menarik.Sesederhana itu saja. Padahal kekuatan film Abracadabra justeru terletak pada estetika visualnya. Makanya antara kritik film dengan karya film yang dikritiknya menjadi menjadi ‘tidak nyambung.”
Baca juga: Wabah Virus Covid 19: Masih Adakah Media Arus Utama?
Contoh lain, ada pengamat yang membahas film 1917 karya sutrada Sam Mendes. Dia mempersoalkan kenapa yang diminta membawa surat dua prajurit muda Schofield (George Mckaey) bersama Blake (Dean Charles Chapma) dan bukan prajurit atau perwira yang lainnya. Sebaliknya mereka sang pengamat sama sekali tidak menelaah dari aspek filmis atau sinematografisnya. Tidak mempersoalkan untuk seluruh film ini setiap satu adegan dibuat dengan sekali pengambilan gambar.
Akibat pendekatan semacam itu, jarang sekali kritikus film yang meninjau dari segi seni film sendiri. Mereka melupakan pada hakekatnya film adalah bahasa seni gambar hidup. Film adalah piktografi atau susunan gambar-gambar dan simbol-simbol yang dilengkapi dengan berbagai unsur lainnya seperti musik dan sebagainya. Itulah sebabnya kita menjadi mafhum, jarang sekali “kritikus film” yang mampu memberikan penafsiran terhadap adegan atau gambar dalam film. “Kritik film” akhirnya berubah menjadi kritik bergenit-genit terhadap berbagai hal yang tidak langsung merujuk kepada eksistensi film sebagai sebuah karya film.
Kurang Pengetahuan Teori Film
Ada banyak faktor kenapa hal ini terjadi. Pertama, para “kritikus film” itu sangat kurang mempelajari sejarah dan perkembangan film. Pengetahuan mereka terhadap seni film masih minim, sehingga kekurangan pisau bedah yang tepat dan tajam. Mereka tidak dapat menelusuri karya-karya film yang dihadapi dengan melakukan upaya komprehensif terhadap jejak karya-karya film lainnya.
Kedua, para “kritikus film” minim pemahaman terhadap pemikiran dan teori-teori kesenian pada umumnya, dan teori-teori film pada khususnya. Dengan begitu, pengetahuan mereka untuk menggali makna film juga terbatas.
Ketiga, memang kurang ada tradisi “kritik film” di Indonesia yang kuat dan mengakar. Di lingkungan pendidikan formal film sekalipun, masih kurang jurusan dan mata kuliah kritik film. Akibat selanjutnya sebagai konsekuensi, belum ada tradisi panjang pergumulan pemikiran dalam dunia kritik film Indonesia, termasuk belum muncul pemahaman yang tepat bagaimana membuat kritik film. Dampaknya, membuat jarang pula lahir kritikus-kritikus film. Para penulis “kritik film” atau pengamat film lebih banyak coba-coba dalam kegelapan.
Kurang Sexy
Keempat, faktor lainnya, menjadi kritikus film kurang “sexy” dibanding dengan jadi pelaku film seperti pemain, sutradara atau penulis skenario. Kritik film berada di belakang “panggung” film, sedangkan pelaku film berada di dalam sorotan frame publik, sehingga orang lebih cenderung merasa lebih tertarik menjadi pelaku film langsung, ketimbang menjadi kritikus film. Pelaku film dapat menggerek popularitas diri, sedangkan kritikus film lebih sering harus menyusuri jalan yang sunyi tanpa sorotan publik.
Belum lagi ada sekelompok orang dengan pongah mengatakan, “Di Indonesia belum ada kritikus film!” Hal ini membuat belum apa-apa ada penulis yang merasa “keder” kalau eksistensi kritikus film tidak diakui. Tentu mental mental rendah diri seperti itu memang tidak layak jadi kritikus film. Apalagi sejarah perfilman Indonesia sejak lama sudah memiliki kritikus film. Misalnya Soeraun yang sejak awal sudah selalu mengkritik film Indonesia, sesuai dengan bahasa zamannya.
Kelima, kritikus film juga tak jarang harus menghadapi perilaku “bermusuhan” dari produser, sutradara atau personil film lain yang karyanya mendapat penilaian kurang baik atau buruk dari kritikus film. Mereka banyak yang tidak suka filmnya dikritik. Para insan film seringkali lebih suka diberi pujian. Nah, daripada menghadapi kemungkinan berhadapan dengan banyak pihak yang tidak suka, kebanyakan pengamat film menghindari menjadi kritikus film.
Keenam , boleh jadi memang para “pengamat film” atau “calon kritikus film” sendiri malas mengasah diri dengan riset dan terus menerus belajar serta tetap konsisten melahirkan karya kritik film. Mereka lebih mencari jalan pintas ketimbang harus melalui proses panjang pergelutan pemikiran dan penyempurnaan karya-karya kritik film. Mereka terbuai proses instan. Buat apa capai-capai dengan hasil yang belum tentu mendapat aspirasi dari publik, dan bahkan ada kemungkinan dimusuhi orang yang dikritik.
Baca juga: Jaringan Cinema 21 Bakal Kembali Tayangkan Film
Berbagai faktor-faktor itu membuat jarang sekali muncul kritikus film “murni:” Kritikus film yang menelaah film sebagai sebuah karya seni multi media dan multi dimensi. Mereka pun akhirnya membuat kritikus film yang tidak fokus kepada aspek-aspek film, melainkan seperti melakukan telaah sastara saja. Oleh karena itu, kita sulit menemukan pembahasan film yang menerangkan kesinambungan planing information, kenapa dalam suatu adegan tertentu kamera harus diambil dari atas, dari bawah atau bergerak dan apa maknanya. Apakah sudut pandang kamera hanya semata-mata pencari efek estetik ataukah ada maksud lain. Demikian pula kita jarang menemukan tulisan yang menerangkan bagaimana “tone” film.
Padahal manakala menilai film, kita seharusnya pertama-tama menilai bagaimana film menyajikan rangkaian gambarnya. Bagaimana cerita dikemas dalam gambar. Bagaimana karakter pemain divisualkan film. Apa yang membuat akting pemain kelihatan menjadi kuat, atau kenapa musiknya memperkuat atau mengurangi makna film.
Relevansi Sosial Tetap Penting
Tentu saja, dalam kritik film relevansi film dengan sosial, budaya dan politik juga menjadi sesuatu yang penting dibahas dan dikemukan. Jangan disalahtafsirkan seakan-akan kritik film harus semata-mata membahas aspek teknikal film belaka dengan mengabaikan unsur sosial, budaya atau psikologis. Semua aspek itu tetap perlu ditemukan dalam kritik film, agar kritik film tidak menjadi kering, namun jangan dilupakan, berbeda dengan kritik sastra, dalam kritik film semua hal itu tetap harus dikaitkan dengan filmnya sendiri dan bukan pembahasan yang terpisah.
*Wina Armada Sukardi, kritikus film
BACA JUGA: Cek FILM & MUSIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini