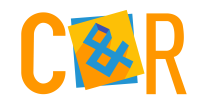Ceknricek.com — Jumat (19/7), Kementerian Pariwisata mengundang wartawan untuk menghadiri sekaligus menyaksikan pemutaran trailer film “Bali: Beats of Paradise”, karya sutradara Livi Zheng. Ini adalah yang kedua kalinya Kemenpar membawa Livi Zheng ke hadapan wartawan, di Balairung Soesilo Soedarman, auditorium milik Kemenpar yang biasa digunakan untuk acara seremonial. Sebelumnya, Livi diundang dan diperkenalkan pada wartawan, 17 Juli, oleh Menteri Pariwisata, Arief Yahya.
Foto : Istimewa
Entah siapa yang diuntungkan dalam acara itu, apakah Livi Zheng atau Kemenpar. Karena tanpa keterlibatan Kemenpar, Livi sudah jalan sendiri. Gadis kelahiran Blitar, Jawa Timur ini sudah memperkenalkan Indonesia di Amerika, melalui karya-karyanya. Sebagai orang Indonesia –meski dia datang dari etnis yang sering dituding anasionalis– Livi mengaku resah, ketika pertama kali datang ke Amerika, banyak sekali orang yang tidak tahu Indonesia.
“Sejak itu saya bertekad akan menampilkan budaya Indonesia melalui film-film saya,” kata Livi ketika Dirman 91 mewawancarainya, dua pekan lalu di Hotel NAM Kemayoran, Jakarta.
Kemenpar sudah pasti harus berterima kasih kepada Livi. Karena tanpa dukungan resmi pemerintah –biasanya kalau dapat dukungan resmi akan dapat bantuan finansial juga — Livi dengan sukarela mempromosikan budaya dan pariwisata Indonesia. Bandingkan dengan biaya pemasangan logo “Wonderful Indonesia” di badan bus di beberapa kota besar di Eropa dan Amerika. Belum lagi pengiriman misi kebudayaan yang menguras biaya.
Sementara banyak sineas dan produser film Indonesia tergila-gila syuting di luar negeri –mungkin karena menganggap penonton film Indonesia masih norak– biasanya karena alasan biaya dan perizinan yang lebih mudah, Livi memilih kembali ke Indonesia.
Bagi Livi, budaya dan keindahan alam Indonesia adalah kekayaan luar biasa, yang tidak ada habisnya untuk dieksplorasi. Dia bahkan sampai bingung membuang shot-shot yang telah diambil untuk film “Bali: The Beats of Paradise”.
Foto : Istimewa
Nyatanya, dia tidak salah perhitungan. Filmnya “Bali: Beats of Paradise” mendapat sambutan menggembirakan. Film itu disaksikan 500 penonton ketika premier di Amerika, diputar di bioskop terbesar di dunia ketika premier di Korea; dibeli oleh Baidu, unicorn China yang memiliki platform online dengan 90 juta pelanggan; dan dibeli oleh Singapore Airlines.
Siapa sih Livi Zheng? Mengapa dia beberapakali menjadi tamu penting bagi orang-orang penting di Indonesia?
Wikipedia menulis: Zheng lahir di Blitar, Jawa Timur, Indonesia pada 3 April 1989. Pada usia empat tahun, ia dan keluarganya berpindah ke Jakarta, Indonesia.
Di Indonesia dia mengawali kariernya sebagai produser dan pemain pengganti dalam sinetron serial berjudul Laksamana Cheng Ho (2008), lalu sekolah ke Beijing dan melanjutkan ke Amerika masuk Universitas Washington, di mana ia mendapatkan gelar sarjananya dalam bidang ekonomi dalam dua setengah tahun, dan masuk dalam Komunitas Kehormatan Ekonomi Internasional. Lalu melanjutkan ke Sekolah Seni Sinematik di South California University.
Foto : Istimewa
Menurut pengakuan Livi, selain sekolah, di Amerika dia juga sempat mengajar ilmu bela diri dan mengikuti kejuraan bela diri di beberapa negara bagian, bersama adiknya, Ken, yang juga berkarier di film sebagai penulis.
Meskipun telah menyelesaikan pendidikan ekonomi dan menjadi warga kehormatan bidang ekonomi di Amerika, Livi lebih tertarik dengan dunia film. Saat itu usianya 23 tahun. Ia juga masih tercatat sebagai mahasiswi ekonomi di University of Washington-Seattle. Dengan modal dengkul, Livi Zheng membuat film pertamanya.
Sepanjang kariernya di film, Livi Zheng telah membuat beberapa film, baik sebagai produser, sutradara maupun menjadi artis. Ia telah membuat beberapa film, baik di Amerika maupun di Indonesia. Livi memulai debut film layar lebarnya pertama Brush With Danger, tahun 2014, yang pernah diedarkan di Indonesia.
Foto : Istimewa
Memang belum banyak yang dihasilkan Livi sebagai sineas. Namun keberhasilannya memulai karier di Amerika membuatnya berbeda dengan banyak sineas dalam negeri, yang tentunya juga ingin mendapatkan pengakuan dari luar negeri, khususnya Amerika.
Amerika adalah sebuah “great wall” yang sangat panjang, terlalu sulit untuk ditembus oleh seniman-seniman yang memiliki bakat hebat dari Indonesia. Karena hebat di Indonesia, dalam ukuran Amerika belum masuk hitungan. Penyanyi kawakan Indonesia, Bob Tutupoli pernah menceritakan betapa sulitnya berkarier di Amerika, sehingga ia yang dikenal sebagai penyanyi hebat di Indonesia, pada tahun 1969 hanya bisa menyanyi di Restoran Ramayana, milik Pertamina di kota New York, Amerika Serikat. Bob Tutupoli akhirnya kembali ke Indonesia.
Di bidang film, Indonesia juga terus mencoba keangkeran negeri pemilik industri film nomor wahid di dunia itu. Sejak tahun 1986 Indonesia selalu mengirimkan film-film Terbaik versi Festival Film Indonesia, untuk diikutsertakan dalam kompetisi Best Foreign Language Film (Film Berbahasa Asing Terbaik).
Terakhir yang diikutsertakan film “Marlina, Pembunuh Dalam Empat Babak” karya Mouly Surya. Sayangnya sampai saat ini Indonesia selalu gigit jari, walau pun film yang dikirim itu selain Pemenang FFI, diseleksi lagi oleh tim yang terdiri dari insan film berbagai kalangan, termasuk yang sudah mengikuti berbagai festival di luar negeri.
Foto : Istimewa
Apakah Amerika benar-benar tertutup untuk film Indonesia? Tidak juga. The Raid merupakan film produksi Indonesia pertama yang bisa menembus posisi 11 dalam daftar film box office di Amerika pada 2012. Film yang dibintangi oleh Iko Uwais dan Yayan Ruhian itu disutradarai oleh Gareth Evans, sutradara film dari Wales yang aktif di perfilman Indonesia.
Berkat jasa Evanslah perfilman Indonesia makin dikenal. Iko Uwais dan Yayan Ruhiyan yang kemudian ikut merasakan bermain dalam film Hollywood, pantas berterima kasih kepadanya.
Namun harus diingat, film Amerika membutuhkan skill orang-orang seperti Iko Uwais dan Garet Evas, juga Joe Taslim, yang memiliki keahlian beladiri, bukan karena kemampuan sebagai aktor. Untuk aktor non laga, kesempatan nyaris tertutup. Aktor sekelas Ray Sahetapi pernah diundang syuting, tetapi tidak muncul di film.
Foto : Istimewa
Livi Zheng, entah apapun caranya, berhasil berkarya di Amerika. Tentu saja jalan yang ditempuh tidak mudah. Duit bukan segala-galanya di Amerika. Ketika pertama kali ingin membuat film, tawaran Livi 32 kali ditolak oleh pekerja film di Amerika, mengingat ia belum memiliki portofolio meyakinkan.
“Banyak yang ngomongin nggak gampang untuk jadi sutradara. Sampai mentorku juga ngomong, ‘you’re everything wrong but a director because you’re Asian, woman and you’re young (kesalahanmu bukan menjadi sutradara, melainkan karena dirimu berasal dari Asia, perempuan dan kau masih muda),” ungkap Livi belum lama ini.”
32 kali ditolak, seperti suatu pengalaman yang menyakitkan. Sineas Indonesia mungkin sudah patah semangat jika dua kali saja mengalami penolakan. Karakter orang Indonesia seperti yang ditulis Mochtar Lubis dalam bukunya, “Manusia Indonesia”, sangat tidak bisa menghadapi kenyataan seperti itu. Tetapi Livi adalah seseorang yang datang dari etnis yang dikenal gigih dan ulet. Penolakan baginya adalah sebuah tantangan. Livi terus maju, sehingga tawarannya untuk menjadi juragan bagi pekerja film di Amerika, diterima.
Foto : Istimewa
Berhasil membuat film di Amerika, Livi kembali ke Indonesia. Dengan disain promosi dan publikasi yang jitu, dia cepat dikenal di Indonesia. Berbekal karya dan kemampuan diplomasi khas etnis Tionghoa, Livi berhasil bertemu dengan orang-orang penting di Indonesia. Mulai dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kapolri Tito Karnavian, Menteri Pariwisata Arief Yahya dan pejabat-pejabat lain di tingkat yang lebih rendah.
Livi juga rajin bersilaturahmi, tanpa menyombongkan diri telah membuat film di Amerika. Livi datangi tokoh-tokoh dan organisasi film yang membuka pintu silaturahmi dengannya, dia tidak pernah menolak dan merendahkan media yang ingin mewawancarainya.
Berbanding terbalik dengan sambutan pejabat-pejabat pemerintahan. Di mata orang film dan kritikus film hebat Indonesia, Livi dianggap bukan siapa-siapa. Ada semacam resistensi dari kalangan film di Indonesia yang memang sering membuat dikotomi. Banyak yang kasak-kusuk untuk mencari titik lemah Livi Zheng. Apakah dari portofolio atau kadar kesineasannya.
Kalimat seperti, “Livi itu siapa?” atau sebutan “Sineas Hollywood” dengan nada merendahkan dan sebagainya, sering terdengar, bahkan dari mereka yang mungkin menjejakan kaki di Amerika saja belum pernah.
Foto : Istimewa
Livi juga bukan tidak sadar dengan pandangan miring terhadap dirinya. Tetapi dia tidak peduli. Dia tetap gadis yang humble. Setidaknya di mata jurnalis. Dia dengan jujur mengakui kelemahannya, termasuk mengaku 32 kali ditolak oleh pekerja film di Amerika. Kalau di sini hal itu mungkin dianggap aib dan perlu disembunyikan rapat-rapat. Tetapi Livi menceritakannya kepada siapa saja yang mau mendengarnya.
Kita mungkin perlu mengubah cara pandang terhadap Livi. Katakanlah sebagai sineas dia belum memenuhi ekspektasi, tetapi melalui film-filmnya setidaknya Livi agen telah berjasa memperkenalkan Indonesia. Kalau tugas itu diserahkan kepada sineas yang ada di Indonesia, pasti akan tinggi argonya.
Dan Livi terus menggali kekayaan Indonesia untuk karya-karyanya, sementara banyak sineas di Indonesia terus bergerak ke Barat untuk ditampilkan dalam filmnya. Kini, Livi menjadi agen Walt Disney untuk Asia Tenggara.