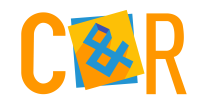Ceknricek.com– Hari Kamis, 18 Agustus 2022 yang lalu, saya bertamu ke kantor Gubernur Lemhannas, Andi Widjojanto. Selain maksud silaturahmi, kedatangan saya waktu itu juga untuk menyampaikan pikiran atas sejumlah persoalan geopolitik, terutama terkait potensi eskalasi militer di kawasan Indo-Pasifik. Selain berbincang mengenai soal-soal militer, obrolan kami kemudian juga menyinggung soal kepolisian.
Saya kebetulan belum lama ini pernah menulis working paper mengenai pentingnya melanjutkan reformasi Polri. Mencuatnya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang jenderal polisi kepada ajudannya belum lama ini, yang kemudian telah membuka banyak kebobrokan di lembaga kepolisian, baik di pusat maupun di daerah, seharusnya bisa memancing kita untuk mendiskusikan masalah ini secara lebih mendalam.
Polisi dan Rongrongan terhadap Demokrasi
Dalam beberapa tahun terakhir, isu mengenai kebrutalan polisi memang tengah menjadi persoalan di banyak negara demokrasi, termasuk di negara-negara paling maju sekalipun. Penggunaan cara-cara agresif, seperti kekerasan, gas air mata, peluru karet, bahkan hingga penggunaan senjata berat untuk menghadapi aksi protes masyarakat sipil, kini tidak lagi dianggap aneh, sehingga menggelisahkan aktivis demokrasi dan masyarakat sipil secara luas.
Di Perancis, misalnya, kita ingat selama terjadi Gerakan Rompi Kuning (Yellow Jackets Movement, atau Mouvement des Gilets Jaunes), yaitu aksi protes masyarakat atas kenaikan harga BBM, tingginya biaya hidup, serta buruknya sistem perpajakan yang berlangsung pada akhir tahun 2018 silam, polisi telah menangani aksi unjuk rasa tersebut dengan cara-cara agresif dan penuh kekerasan.
Hal serupa juga terjadi di Inggris. Beberapa kolumnis dan pengamat politik menyebut jika Inggris telah terperosok ke dalam lumpur otoritarianisme karena polisi Inggris kini menangani aksi protes masyarakat, terutama yang paling menonjol adalah dalam menghadapi Insulate Britain—sebuah gerakan protes dengan isu lingkungan yang sering melakukan aksi dengan memblokade jalan—dengan cara kekerasan dan bahkan pemenjaraan.
Amerika Serikat (AS), yang dulu selalu dieluk-elukan sebagai negara kampiun demokrasi, kini justru tercatat sebagai negara dengan kasus pembunuhan oleh polisi yang tertinggi di dunia. Selain kasus kematian George Floyd pada 2020, yang telah menyulut kerusuhan di mana-mana, kasus serupa banyak terjadi di AS. Merujuk pada data yang dikumpulkan oleh Mapping Police Violence (2022), sepanjang tahun 2022 saja, misalnya, polisi AS telah “membunuh” 286 orang, di mana peluang orang kulit hitam untuk terbunuh oleh polisi 2,9 kali lebih besar dibandingkan orang kulit putih.
Secara kumulatif, antara tahun 2013 hingga 2021, polisi AS telah membunuh 9.906 orang. Sebagai perbandingan, pada periode yang sama setidaknya 254 orang tewas di tangan polisi Kanada. Sementara, di beberapa negara, seperti Finlandia dan Norwegia, misalnya, sudah bertahun-tahun lamanya tidak terjadi pembunuhan oleh polisi.
Jika di negara-negara maju saja situasinya demikian, maka kondisi di negara-negara berkembang tentunya lebih buruk lagi. Pada Oktober 2020, misalnya, pasukan keamanan Nigeria dilaporkan telah melepaskan tembakan langsung ke arah pengunjuk rasa yang menyerukan reformasi polisi, sehingga menewaskan dua belas orang. (bersambung)