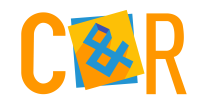Ceknricek.com — Pelaksanaan car free day (CFD) di sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin, DKI Jakarta, yang kembali digelar pada Minggu (21/6/2020), menimbulkan reaksi keprihatinan. Hal ini karena kerumunan warga yang hadir di acara CFD terlihat begitu ramai dan menumpuk. Dengan demikian, warga di acara CFD secara efektif mengabaikan protokol jaga jarak (physical distancing) terkait Covid-19.
Padahal pandemi Covid-19 belum berakhir. Memang, ada pelonggaran pelaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dalam rangka menyambut kondisi New Normal. PSBB dimaksudkan untuk menghidupkan kembali ekonomi secara bertahap, agar warga yang sulit mencari nafkah sehari-hari akibat terkungkung aturan ketat PSBB, bisa mulai kembali beraktivitas.
Tetapi, ini bukan berarti ancaman penularan virus sudah selesai. New Normal harus diartikan sebagai situasi-kondisi baru, di mana pengertian “Normal” mendapat makna baru. Tindakan kehati-hatian dan disiplin, dalam perilaku pencegahan penularan virus, tetap harus diterapkan di era New Normal.
Namun, karena istilah “New Normal” ini terkesan kurang jelas dan ditafsirkan secara beragam oleh warga, Pemerintah lalu meluncurkan tagar baru dengan pesan yang lebih jelas dan gamblang: #AdaptasiKebiasaanBaru. Artinya, di era New Normal, warga secara bertahap boleh mulai kembali beraktivitas, tetapi tak bisa tidak harus menyesuaikan diri dan mengadopsi kebiasaan baru.
Baca juga: Syahganda Nainggolan: Istilah New Normal Indonesia Beda dengan WHO
Kebiasaan baru itu, misalnya: rajin mencuci tangan dengan sabun, selalu mengenakan masker, mengambil jarak fisik, menghindari kerumunan dan sentuhan langsung dengan orang sekitar, dan sebagainya.
Menurut Mendagri Tito Karnavian, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah banyak menyosialisasikan protokol kesehatan untuk masa New Normal yang produktif dan aman. Hanya saja, perlu terus ada sosialisasi untuk mengantisipasi anggapan masyarakat, yang mengira pandemi Covid-19 sudah berakhir. Sebab, adaptasi terhadap kebiasaan baru tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.
Disiplin dan Protokol Kesehatan
Pemerintah boleh saja punya program-program bagus tentang bagaimana tahapan-tahapan memasuki era New Normal, yang kini dikonkretkan dengan tagar #AdaptasiKebiasaanBaru. Namun, selama masyarakat kita tidak mau mematuhi protokol standar pencegahan Covid-19, tampaknya semua pengaturan itu akan sia-sia saja.
Kita melihat penyebaran Covid-19 belum menunjukkan penurunan kurva yang signifikan. Tetapi apa mau dikata, kebutuhan ekonomi juga tidak bisa menunggu. Banyak warga yang nafkah hidupnya tergantung dari kerja harian. Jika disuruh terus diam di rumah tanpa kejelasan, dan tanpa ada dukungan dari sumber luar, jelas tidak mungkin.
Maka, pilihan yang sudah diputuskan adalah secara bertahap menghidupkan kembali aktivitas ekonomi warga, seraya mempertahankan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah/membatasi/mengurangi penyebaran Covid-19.
Persoalannya, bagaimana menjaga atau memastikan agar warga betul-betul berdisiplin, melaksanakan protokol kesehatan tersebut? Aparat tidak mungkin dikerahkan terus-menerus di semua tempat, pada semua keadaan, dan setiap waktu untuk memastikan penegakan aturan itu. Jumlah aparat terbatas dan sumber dayanya juga tidak memungkinkan.
Merespons hal itu, dalam tulisan ini, penulis mengusulkan pendekatan budaya sebagai caranya. Aturan hukum semata, seberapapun kerasnya, tidak akan memadai untuk menegakkan protokol Covid-19 dan #AdaptasiKebiasaanBaru. Dalam pendekatan budaya ini, kearifan lokal (local wisdom) termasuk unsur yang perlu didayagunakan, untuk mendukung #AdaptasiKebiasaanBaru.
Strategi Kebudayaan
Namun apa sebenarnya yang dimaksud dengan pendekatan budaya tersebut? Kebudayaan adalah kategori yang bisa mencakup begitu banyak hal. Ada sebanyak 176 definisi mengenai “kebudayaan,” yang muncul dalam berbagai tulisan, yang pernah dikumpulkan oleh pakar antropologi budaya A.L. Kroeber dan C. Kluckhohn (1952).
Menurut definisi awal yang sangat berpengaruh dari Sir Edward Taylor (1871), kebudayaan merupakan keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan semua kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh oleh seseorang, sebagai anggota masyarakat.
Maka, kebudayaan terdiri dari seluruh pola-pola yang dipelajari –mulai dari bertindak, merasakan, dan berpikir—yang dialami bersama secara sosial oleh para anggota masyarakat tertentu. Seseorang menerima kebudayaan sebagai bagian dari warisan sosial, dan pada gilirannya, bisa membentuk kebudayaan kembali dan mengenalkan perubahan-perubahan, yang kemudian menjadi bagian dari warisan generasi yang berikutnya.
Baca juga: Pengamat Sarankan Pemerintah Bangkitkan Budaya Bersepeda
Definisi Taylor ini kemudian dianggap terlalu luas. Koentjaraningrat (2003) menyarankan, agar kebudayaan dibeda-bedakan sesuai dengan empat wujudnya. Jika disimbolkan sebagai empat lingkaran konsentris, maka wujud kebudayaan –mulai dari tampilan luar yang paling mudah dilihat, ke pusat atau inti yang paling dalam– berturut-turut adalah sebagai berikut: (1) artifacts, atau benda-benda fisik; (2) sistem tingkah laku dan tindakan yang berpola; (3) sistem gagasan; (4) sistem gagasan yang ideologis.
Jika berbagai definisi tentang hakikat kebudayaan itu dikumpulkan, pastilah tak akan ada habis-habisnya. Van Peursen menggunakan pendekatan yang berbeda. Ia menyarankan, tidak perlu terpaku pada definisi-definisi teoretis yang sudah begitu banyak itu. Namun, kata Van Peursen, akan lebih produktif jika pertanyaan yang diajukan adalah apa yang dapat kita perbuat dengan kebudayaan.
Filsafat kebudayaan modern tidak menyibukkan diri dengan konsep-konsep teoretis, tetapi meninjau kebudayaan terutama dari sudut policy tertentu. Yaitu, sebagai suatu strategi kebudayaan atau masterplan bagi masa depan.
Manusia modern hendaknya disadarkan tentang kebudayaannya. Hal ini berarti ia secara aktif diharapkan turut memikirkan dan merencanakan arah yang akan ditempuh oleh kebudayaan yang manusiawi.
Sebagai Kata Kerja
Pergeseran kedua terjadi dalam isi konsep kebudayaan. Kini kebudayaan dipandang sebagai sesuatu yang lebih dinamis, bukan sesuatu yang kaku atau statis. Kalau dulu kata “kebudayaan” diartikan sebagai sebuah kata benda, kini lebih sebagai kata kerja.
Kebudayaan bukan lagi pertama-tama sebuah koleksi barang-barang kebudayaan –seperti: buku, gedung, museum, candi, dan seterusnya. Namun, kebudayaan kini terutama dihubungkan dengan kegiatan manusia. Seperti: cara mendidik anak, sidang-sidang parlemen, perilaku birokrasi, dan –dalam kasus kita saat ini—implementasi #AdaptasiKebiasaanBaru.
Dalam pengertian kebudayaan juga termasuk tradisi, dan “tradisi’ dapat diterjemahkan dengan pewarisan atau penerusan norma, adat istiadat, kaidah. Namun, tradisi itu bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah. Tradisi justru diperpadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya.
Manusialah yang membuat sesuatu dengan tradisi itu: ia menerimanya, menolaknya, atau mengubahnya. Itulah sebabnya mengapa kebudayaan merupakan cerita tentang perubahan-perubahan: riwayat manusia yang selalu memberi wujud baru kepada pola-pola kebudayaan yang ada.
Oleh Van Peursen dengan strategi kebudayaannya, konsep kebudayaan telah diperluas dan didinamisasikan. Kebudayaan kini tidak dianggap bersangkutan dengan sekelompok kecil ahli saja, tapi setiap orang ingin mencoba mencari atau menangani kekuatan-kekuatan yang turut membentuk kebudayaan. Setiap orang ini termasuk Anda dan saya.
Implikasi yang Luas
Maka kalau kita bicara tentang strategi kebudayaan, dalam upaya menegakkan perilaku disiplin terhadap protokol Covid-19, itu implikasinya sangat luas. Pengertian kita tentang kebudayaan harus lebih dari sekadar pemahaman populer biasa. Kebudayaan bukanlah sekadar baju batik, tari-tarian daerah, candi, keris, dan sebagainya, yang sering dijadikan komoditi pariwisata.
Sekadar contoh, tugas Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud RI adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya.
Pengertian “…dan kebudayaan lainnya” itu sebetulnya sebuah kerja besar. Misalnya, perilaku korupsi yang akut di berbagai bidang dan tingkatan saat ini –mengutip Bung Hatta– sudah “membudaya.” Maka, cara melawan perilaku korupsi tidak cukup dengan sekadar memperberat ancaman hukuman, tetapi juga dengan strategi kebudayaan. Karena budaya itu diciptakan oleh manusia, maka manusia pula yang bisa mengubahnya dengan membentuk budaya baru.
Baca juga: Rocky Gerung:Soal New Normal, Itu Kebijakan yang Mondar Mandir
Kembali ke topik #AdaptasiKebiasaanBaru, perilaku warga yang sesuai dengan protokol kesehatan di era New Normal ini harus dijadikan bagian dari strategi kebudayaan. Sedangkan, aturan hukum, pendidikan, sosialisasi nilai-nilai, komunikasi publik, kearifan lokal, dan sebagainya, semua itu merupakan unsur-unsur yang harus dibenahi, dikelola, dan ditingkatkan dalam kerangka besar strategi kebudayaan.
Dalam konteks ini, bukan cuma Ditjen Kebudayaan yang harus berperan, tetapi juga semua kita. Semua kalangan bisa dilibatkan dalam kerja besar ini: seniman, penulis, wartawan, politisi, artis, pendidik, pengusaha, buruh, mahasiswa, aktivis LSM, ulama, rohaniwan, tokoh adat, dan sebagainya. Masing-masing berperan sesuai dengan posisi dan kapasitasnya.
Strategi kebudayaan, untuk bisa diimplementasikan, tentu saja harus dirumuskan dalam berbagai langkah aksi implementatif yang lebih rinci dan konkret. Tetapi itu sudah di luar kapasitas artikel pendek ini untuk menjabarkannya. Ini akan menjadi kerja kita bersama, bukan cuma kerja pemerintah. Sebuah kerja besar dalam kerangka strategi kebudayaan.
#Penulis adalah mantan jurnalis Harian Kompas, Executive Producer Trans TV, dan alumnus S3 Filsafat Universitas Indonesia. Saat ini Redaktur Senior di Majalah Industri Pertahanan ARMORY.
BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini