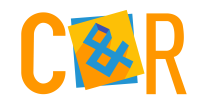Ceknricek.com — Salah satu persoalan kita hari ini adalah rasa panik yang kronis. Segala sesuatu ingin diselesaikan cepat. Tanpa upaya pemahaman persoalan secara menyeluruh. Apalagi integrasi antar satu dengan yang lain.
Dalam hal bangsa kita, masing-masing masalah itu sudah berkembang jauh. Sedemikian rupa justru menyesuaikan diri dengan “keadaan”. Berkamuflase hingga menciptakan mutan yang berupa ilusi. Seolah persoalan itu wajar dan biasa. Hingga akhirnya kita menyikapi sebagai keniscayaan belaka.
Saya bisa menjelaskannya panjang-lebar. Tapi mungkin lain waktu saja ya. Kita fokus mengarah pada “disrupsi Pancasila” yang saya maksud dulu.
***
Akar persoalan paling utama bangsa kita — sebagaimana umumnya bangsa-bangsa lain — adalah tentang pembiayaan.
Lazimnya, tentu berkaitan dengan sumber yang digunakan untuk membiayai. Kita maklum, hampir sepanjang masa, biaya yang dibutuhkan bangsa kita selalu tekor. Khususnya jika mengandalkan hasil keringat.
Pada dasarnya, pembiayaan apa pun selalu bersumber dari 4 hal. Pertama, kekayaan atau modal yang dikuasai. Kedua, hasil usaha yang dilakukan. Ketiga, pinjaman atau hutang. Keempat, sumbangan atau belas kasih yang diberikan pihak lain.
Jika hasil keringat atau usaha tak mencukupi, kita terpaksa menggadaikan modal. Atau malah mengobralnya supaya bisa menutup kebutuhan.
Pinjaman biasanya diperoleh dengan menggadaikan modal. Tentu harus dibayar kembali. Tapi yang paling penting diingat, pinjaman bisa diperoleh atau dikabulkan jika pihak yang memberikan “percaya” bahwa kita mampu mengembalikannya. Itu pun setelah melalui pertimbangan yang lebih utama lagi. Yakni, manfaat dan keuntungan “lebih luas” yang bisa diperoleh pihak yang meminjamkan. Singkat kata, no free lunch lah.
***
Tapi kekayaan kita semakin menipis. Untuk kebutuhan sendiri pun tak cukup lagi. Seperti minyak bumi.
Ada kekayaan lain yang mungkin masih berlimpah. Tapi kita tak punya kemampuan mendayagunakan potensi nilai tambahnya sendiri. Kita belum berdaulat. Campur tangan dan kesediaan orang lain untuk menggarapnya, sangat dibutuhkan. Tanpa itu, mungkin tak berarti apa-apa.
Baca juga: Salam Pancasila
Di sinilah kekeliruan terbesar yang berlarut-larut dibiarkan sejak merdeka.
Setiap pemimpin negara kita memang selalu menyadarinya. Sukarno dulu mengirim banyak putra-putri terbaik belajar ke manca negara. Diantaranya Rusia. Agar bangsa kita menguasai teknologi yang dibutuhkan untuk mengembangkan sumberdaya yang ada.
Tapi pergolakan politik selalu menyita perhatian yang lebih besar. Menyingkirkan gagasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan untuk menopang pembangunan, ke lapis kedua. Ketiga. Bahkan ke sekian di bawahnya.
Suharto juga bernasib sama. Di tengah nikmat minyak bumi dan hegemoni kekuasaan di masa-masa awalnya, dia menarik Habibie pulang ke tanah air. Jadi anak emas sekaligus maskot ilmu pengetahuan dan teknologi.
Begitu banyak pemuda-pemudi Indonesia di masa itu disekolahkan ke luar negeri tak termanfaatkan dengan baik untuk kepentingan bangsa. Padahal, latar belakang pembiayaan penganggarannya adalah untuk itu.
Absurditas tersebut terjadi karena tak disertai kesungguhan tekad mengembangkan hingga menegakkan kedaulatan sains dan teknologi itu sendiri. Atas nama stabilitas — kemudian hari Suharto justru turut menikmati kekeliruan itu ketika keluarganya berbisnis — upaya menegakkan kedaulatan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tetap digeser ke prioritas yang lebih rendah.
Iklimnya tak pernah terbentuk dan berpihak.
Sains dan teknologi akhirnya diperlakukan seperti kosmetika. Untuk menampilkan “kecantikan” yang semu. Supaya sedap dipandang dan menggoda. Bukan bagian dari pengembangan “inner beauty.”
***
Kembali ke pokok soal — yakni kebutuhan pembiayaan dan ketersediaan sumbernya — keadaan kita justru semàkin runyam ketika kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat meningkat. Tapi semua itu berlangsung karena alasan politis yang mengedepankan stabilitas ketahanan dan keamanan secara keliru. Sehingga terjadilah pergeseran besar-besaran dari masyarakat agraris ke urban. Hal yang kemudian mempengaruhi standar dan kualitas tuntutan hidup yang harus ditopang negara.
Sementara itu, karena kedaulatan iptek tadi tak sungguh-sungguh dikerjakan, produktivitas yang mampu dicapai masyarakat kita, semakin jauh dari kata sepadan. Hal yang kemudian turut menjelaskan, mengapa defisit neraca perdagangan kita terus melebar, dan seterusnya.
Kita memang bermasalah dalam hal kemampuan meningkatkan sumber pendapatan mandiri. Baik dari kekayaan yang dikuasai maupun hasil usaha yang dilakukan. Nyatanya memang tak kunjung mampu mengimbangi laju kebutuhan pembiayaan yang semakin besar. Tapi juga semakin kompleks.
Baca juga: Omnibus Law Cilaka
Alasan dibalik stabilitas politik — diam-diam maupun terang-terangan — kemudian menyuburkan perilaku korupsi yang merajalela. Ditambah lagi dengan birokrasi pemerintahan yang semakin kusut.
Negara kita semakin kehilangan fokus.
Administrasi dan perizinan sedemikian rupa diperlakukan sehingga menempati posisi yang jauh lebih penting dari gagasan, inovasi, dan kreatifitas. Padahal, ketiga unsur itulah yang dibutuhkan oleh habitat yang sehat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pergeseran paradigma tersebutlah yang menjadi penyebab utama rusaknya atmosfir dunia sains dan teknologi tadi.
***
Dulu kita begitu frustasi menghadapi kekuasaan Orde Baru. Tapi tak berdaya. Karena kekuasaan Suharto sudah merambah ke segala lini. Dia bertahan karena dunia internasional yang berkepentingan dengan Indonesia, mendukungnya. Lewat politik bantuan (hibah) dan pinjaman (hutang).
Segalanya mulai berbalik ketika Cina bangkit dan menyatakan membuka diri pada pertengahan 1980-an. Peta kekuatan ekonomi global pun terancam bergeser.
Banyak teori yg berkembang. Tapi pada intinya, masa indah Barat yang kala itu menggelontorkan bantuan dan pinjaman tanpa batas, segera menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Menjelang 1997, mereka mulai berulah dan mengajukan syarat yang membuat Suharto tak nyaman. Hingga akhirnya kita gagal membayar hutang (default), rupiah runtuh, bahan pokok langka, dan akhirnya memicu Gerakan Reformasi itu.
Seperti Kemerdekaan 1945, Reformasi 1998 bukan “kemenangan” yang direncanakan dengan strategi matang. Terlalu banyak unsur “kebetulan”-nya. Maka pada keduanya, sejarah mencatat berbagai “ketidaksiapan” kita untuk menerima, mengisi, dan memanfaatkan “kemenangan” itu.
***
Salah satu dari sejumlah hal penting yang kita canangkan ketika Reformasi — selain pengakhiran dwifungsi ABRI, pemberantasan korupsi, pelaksanaan pemilu demokratis, dst — adalah Otonomi Daerah.
Sayangnya, pendekatan utama yang mendasari semangat tersebut, adalah soal “distribusi” kekuasaan terhadap sumberdaya alam semata. Bukan soal bagaimana agar potensi daerah bisa berkembang dan lebih bergairah mengupayakan kedaulatan ekonomi berbasis nilai tambah. Hal itu dapat dicermati dari ketentuan perundang-undangan yang mengatur soal Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang mengikutinya. Otonomi seolah diterjemahkan sebatas soal kekuasaan birokrasi terhadap eksploitasi kekayaan alam semata.
Kebijakan yang sedang digadang Joko Widodo hari ini dengan usulan Omnibus Law yang kontroversial itu, bukan hanya bertolak belakang dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Tapi juga mengukuhkan feodalisme birokrasi pemerintah pusat yang mengira dirinya mampu melakukan segalanya. Berbagai gejala pemangkasan, pengkerdilan, bahkan peniadaan semangat pengembangan Otonomi Daerah yang sesungguhnya mulai berlangsung di sana-sini sejak SBY berkuasa, kini dilakukan semakin terang-terangan.
Sebagaimana dijelaskan di atas tadi, momentum Reformasi yang diperoleh secara “kebetulan”, menyebabkan kita tak sungguh-sungguh “siap” untuk mengisinya. Sejumlah jargon yang mengemuka, termasuk otonomi daerah, kemudian berkembang liar. Adalah kesalahan dan kegagalan kita sendiri yang menyebabkannya bermutasi jadi persoalan baru. Terutama setelah keleluasaannya melahirkan berbagai ketentuan daerah yang dinilai kontra produktif dengan kebijakan Nasional.
Upaya menyelaraskan memang perlu dilakukan. Tapi tentunya bukan dalam semangat memangkas, mengkerdilkan, hingga meniadakan upaya pengembangan otonomi daerah itu sendiri.
Berlatar belakang hal tersebut di atas — juga perkembangan zaman yang sekarang tak hanya berlangsung cepat, tapi juga melompat-lompat — adalah gagasan “transformasi perpajakan, disrupsi Pancasila, dan reformasi kedaulatan bangsa” yang ingin saya sampaikan.
Hari ini, kita semua tahu, betapa pajak merupakan sumber paling penting bagi pembiayaan bangsa kita. Hal yang justru masih diperlakukan dan berlangsung seperti masa bangsa kolonial masih menjajah negeri ini. Tentunya dengan segala kosmetika yang menutup “borok-borok”-nya agar tetap terlihat cantik dan menggairahkan. Meski sesungguhnya sedang sekarat.
Maka dari sanalah segalanya bermula. Persoalan maupun solusinya.
BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini