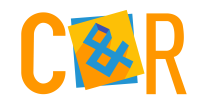Ceknricek.com–Dalam acara Rosi Kompas TV (https://youtu.be/J4whti56CLs?si=kRyn5WZRFvjn1RU), baru-baru ini, menkes membuat pernyataan dan permintaan agar dokter spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan (SpOG) mau menurunkan kompetensi atau mengajarkan operasi Sesar kepada para dokter umum agar bisa menyelamatkan jiwa ibu-ibu yang mengalami kegawatan persalinan di daerah yang tidak memiliki dokter SpOG.
Pernyataan seorang pejabat publik seharusnya muncul berdasarkan data yang benar serta fakta empiris, bukan sekedar dugaan atau bahkan tuduhan bahwa mereka yang menolak ide tersebut dikarenakan takut kehilangan lahan penghasilan. Menkes, tanpa dukungan data yang benar alias ngawur, menyatakan, “Kalau ada 514 RS Kabupaten/ Kota dan kalau SpOG cuma ada di 200 RS lalu bagaimana dengan yang 300 ? Jadi untuk 300 RS ini dokter umumnya mesti diajarin (operasi Sesar/SC)”.
Menkes juga menyatakan kalau dulu boleh (dokter umum melakukan operasi SC), mengapa sekarang tidak boleh? Menkes juga menyampaikan hal perdebatan/ pertikaian di KKI (Konsil Kedokteran) berebut soal kompetensi ini.
Semua pernyataan menkes dalam acara Rosi-KompasTV bila ditelaah baik-baik berdasarkan bukti empiris serta data yang benar, bisa jadi sebuah Pertunjukan Kebohongan dan Kebodohan seorang Pejabat Publik, bahkan sebagian adalah hoaks alias fitnah, misal terkait KKI.
Kebohongan Pejabat Publik, Kesengajaan atau Pura-pura Bodoh demi sebuah Agenda Busuk
Pertama terkait dengan jumlah Dokter Spesialis, SpOG menduduki peringkat kedua terbanyak setelah Spesialis Penyakit Dalam. Menurut data Konsil Kedokteran (KKI), per April 2024, ada sebanyak 5957 SpOG di Indonesia (https://databoks.katadata.co.id) dan menurut data POGI (Perhimpunan Obsteri Ginekologi Indonesia), dari 514 RSU Kab/ Kota hanya 32 RS (6%) yang belum ada SpOG.
Artinya, angka 300 RS yang disampaikan menkes adalah Kebohongan Publik. Pernyataan menkes “kalau dulu boleh (SC dikerjakan oleh dokter umum) mengapa sekarang tidak boleh” artinya menkes bicara atas landasan pikiran sesat (logical fallacy) yang mundur ke masa 40-50 tahun lalu, saat jumlah SpOG belum sebanyak saat ini. Saat itu tidak perlu ada Surat Ijin Praktek (SIP), serta tidak ada keharusan untuk memenuhi syarat SKP (Satuan Kredit Profesi), bagi praktek dokter, kalau dulu boleh kenapa sekarang tidak boleh?
Bicara tentang operasi SC, sebagaimana operasi Bedah lainnya, tentu tidak bisa dilakukan tanpa adanya tim Bedah (Spesialis Anestesi, Spesialis Anak, dan Perawat Bedah terlatih). Pembedahan, sebagai tindakan yang melukai dan mengekspos bagian dalam tubuh manusia, memerlukan kamar bedah dengan segala persyaratan terkait sterilitas ruang dan alat-alat operasi, perlu sistem penyediaan darah, dan tentu semua harus dalam setting Rumah Sakit.
Data kemenkes tahun 2024 menyatakan ada 3155 RS (https://assets.dataindonesia.id) dan 50,27% -nya ada di pulau Jawa. Kalau seorang SpOG dibolehkan bekerja di 3 (tiga) RS, jumlah SpOG yang hampir 6000 orang ini tentu sudah lebih dari cukup untuk semua RS yang ada di negeri ini. Jadi, bila ada RS yang tidak atau belum punya SpOG tentu bukan karena kekurangan SpOG, dan menghadirkan SpOG di RS tersebut adalah tanggung-jawab menkes. Banyak sekali program kesehatan dasar sesuai RPJMN Kesehatan 2020-2024 yang gagal terpenuhi dan semuanya adalah sepenuhnya tanggungjawab menkes.
Saudara menkes, semua orang tahu bahwa dengan semua kekuasaan dan sumber daya yang anda miliki, anda tidak perlu tampil dan mempertontonkan monolog yang penuh kebohongan di depan publik. Atau memang anda sedang berpura-pura bodoh demi menutupi persoalan yang sebenarnya, yaitu ketidakmampuan leadership anda di kemenkes dalam menyelesaikan masalah kronis yaitu distribusi dokter spesialis. Atau, dibalik semua narasi bohong yang manipulatif itu ada lagi agenda busuk lainnya, yaitu menguasai kolegium agar bisa mengatur kompetensi medis spesialistik, demi memperlancar sebuah bisnis kotor pengadaan Kamar Bedah dan Mesin Anestesi di Puskesmas ?
Bagi menkes, Makna Kompetensi Medis disamakan dengan Ketrampilan Vokasi yang bisa dilatih di BLK (Balai Latihan Kerja).Kedua, ternyata jauh lebih mudah mengajari monyet memetik kelapa daripada menjelaskan makna kompetensi medis kepada menkes. Kompetensi harus difahami bukan sekedar bisa melakukan, pernah melakukan, atau berpengalaman melakukan sebuah tindakan medis. Misalkan dirjen yankes yang dokter saya ajak ikut operasi pasien perdarahan otak tiga kali seminggu selama 6 bulan, tentu dia akan bisa bahkan trampil melakukan tindakan operasi itu. Apakah ketrampilan ini bisa disebut kompetensi?
Saat seorang dokter meresepkan obat untuk pasiennya, selain harus faham kegunaan (indikasi) dari obat tsb. dokter juga mesti tahu kondisi seperti apa yang tidak boleh diberikan (kontra indikasi) obat tersebut. Selain itu efek samping/ komplikasi yang bisa timbul dari pemakaian obat itu, serta bagaimana mencegah dan mengatasi bila terjadi efek samping/ komplikasi. Seluruh pengetahuan terkait tindakan meresepkan obat tersebut terangkum dalam ‘body of knowledge’ yang harus melandasi setiap kompetensi medis.
Saat seorang dokter umum dengan pelatihan SC selama 6 bulan melakukan operasi, setelah janin bisa dikeluarkan ternyata plasenta/ ari-ari tak mau lepas atau rahim tak mau kontraksi/ mengecil. Akibatnya perdarahan tidak mau berhenti, tindakan yang mesti dilakukan adalah pengangkatan rahim. Jadi dokter pelaku operasi SC harus trampil pula untuk operasi pengangkatan rahim, atau pasiennya mati kehabisan darah. Komplikasi lain yang tidak jarang terjadi adalah perlengketan dengan usus dan saluran/ kandung kemih. Kalau terjadi robekan pada organ sekitarnya, maka SC bisa berakibat pada komplikasi yang berujung pada kematian atau kecacatan.
Tindakan SC bukan soal menyayat perut dan dinding rahim untuk mengeluarkan janin, seperti pekerjaan seorang Tukang SC. Tapi perlu pengetahuan yang mendalam tentang Anatomi dan Topografi semua organ tubuh yang ada di rongga perut dan rongga panggul, pasokan darahnya serta persarafan yang mengatur fungsi organ-organ tersebut.
Selain itu juga harus dilandasi pemahaman tentang indikasi (alasan medis yang mengharuskan dilakukan SC) dan ada urgensi atau kegawatdaruratan yang mesti dicegah. Bicara tentang SC adalah bicara hal ranah keilmuan, ranahnya para Guru Besar dalam wadah Kolegium, dan bukan ranahnya para pesuruh menkes yang ada di Kolegium Kesehatan, yang ketuanyapun teman menkes yang dicomot tiba-tiba.
Artinya tidak cukup mencomot hanya satu ketrampilan yaitu SC saja, dan menjadikan dokter umum sebagai Tukang SC. WHO menyatakan bahwa kompetensi harus berbasis Pendidikan formal/ terstruktur dan supervisi klinis. Sedangkan menurut WFME prosedur klinis invasif seperti SC tidak boleh dilakukan tanpa pelatihan yang terstandarisasi. Jadi, demi keselamatan masyarakat penerima layanan, dari pada mencomot sebuah kompetensi SC dengan segala resiko komplikasinya, akan lebih baik bila dokter umum tsb. dididik jadi SpOG dengan kompetensi yang jelas dan terstandar.
Tujuan menurunkan AKI dan AKB bisa gagal akibat Kekuasaan yang mengambil alih Ilmu dan Profesi
Seluruh warga negara, dimanapun berada, berhak mendapatkan layanan kesehatan spesialistik yang berkualitas. Tanggung-jawab menkes adalah menghadirkan Fasyankes dengan SDM yang berkualitas, biaya yang terjangkau, dan Akses Layanan yang berkesetaraan dan berkeadilan. Persoalan utama terkait layanan kesehatan reproduksi adalah masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
Sampai saat ini AKI di Indonesia masih pada posisi tertinggi di ASEAN. Berdasarkan Target SDG 2030, AKI harus turun sampai 70/ 100.000 lahir hidup, sedangkan faktanya (Data dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia atau SDKI) AKI th 1991 sebesar 390, th 2012 sebesar 359, th 2015 sebesar 305, th 2020 sebesar 189. Target untuk tahun 2024 adalah 183/ 100.000 Kelahiran Hidup.
Terkait upaya untuk menurunkan AKI dan AKB ini, sesungguhnya beberapa menkes era sebelum ini telah berkolaborasi dengan para ilmuwan dan akademisi yang tergabung dalam POGI dan Kolegium Obstetri-Ginekologi, melaksanakan program-program promosi dan pencegahan seperti PPDGDON (Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri dan Neonatus) untuk para Bidan, PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatus Emergensi Dasar) untuk para Dokter Umum, dan PONEK (Pelayanan Obstetri dan Neonatus Komprehensif) bagi Fasyankes yang punya SpOG.
Bila berjalan baik, PPDGDON dan PONED berperan besar dalam mencegah, mengenali secara dini, dan melakukan penanganan awal serta merujuk pasien dengan potensi kegawatan ibu dan janin ke faskes rujukan yang sesuai menurut jenis dan derajat kegawatan yang dihadapi. Menurut POGI, saat ini program-program tsb. berjalan tidak lebih dari 40% dan ini memperlihatkan bahwa pemerintah (baca: kemenkes) tidak ada keseriusan dalam upaya promotif dan preventif. Jadi jelas bahwa persoalannya bukan soal SC oleh siapa, dan juga bukan soal penolakan Kolegium Obs-Gin untuk menurunkan kompetensi SC pada dokter umum, tapi kegagalan menkes melaksanakan Program Layanan Primer yang berkualitas misalnya PPDGDON dan PONED.
Menurut Prof. Budi Iman Santoso, Guru Besar Obs-Gin FKUI, Ilmu tidak boleh dilihat sebagai sekedar Administrasi, tapi Akumulasi dari Pengetahuan, Pengalaman, dan Etika. Kompetensi bukan sekedar opini, Etika juga bukan soal Ambisi, dan Keselamatan Pasien bukan soal cepat-lambatnya perizinan. Operasi Sesar (SC) itu bukan soal tukar guling kebijakan, dan bukan pula soal memotongnya begini atau begitu, tapi sebuah keputusan klinis antara hidup dan mati bagi ibu dan bayinya. Hemodialisa bukan sekedar soal perizinan, tapi soal infrastruktur, pelatihan, dan penanganan komplikasi. Kraniotomi bukan sekedar soal membuka tulang kepala, tapi sebuah intervensi saraf pusat yang bisa mematikan.
Selaku pejabat publik yang bukan dokter, tidak mengerti Logika Klinis, dan tidak mengetahui bagaimana Ilmu Kedokteran itu dibangun, maka yang kita lihat adalah kebijakan bodoh yang menjerumuskan. Lebih konyol lagi karena menkes tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ketika kekuasaan mencoba mengambil alih Ilmu Pengetahuan dan mengatur profesi tanpa ilmu, yang terjadi bukan reformasi tapi pelampiasan dari sebuah kebodohan yang dibalut kebohongan. Memaksa dokter umum untuk melakukan tindakan spesialistik invasive (SC), sama dengan mengirim tentara ke medan tempur tanpa membawa Peta dan Senjata.
#Zainal Muttaqin, Pengampu Pendidikan Spesialis, Guru Besar Tamu Universitas Kagoshima