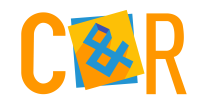Ceknricek.com — Realisasi dari keputusan NU kembali ke khittah 1926 berdasar Surat Keputusan tahun 1985, bermakna bahwa NU tak lagi berpolitik sejak itu. Bagi warga NU, tidak wajib lagi memilih PPP, serta tidak haram mencoblos Golkar dan PDI.
Dengan disepakatinya Nahdlatul Ulama (NU) menarik diri dari aktivitas politik kepartaian (PPP), maka bermakna Muktamar NU di Situbondo telah dimenangkan oleh kelompok pembaru yang dipelopori Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, sebagai realisasi dari keputusan kembali ke khittah 1926, maka berarti NU tak lagi terikat dengan organisasi politik manapun. Selanjutnya, PB-NU mengeluarkan SK No.1/PB-NU/1-1985 tentang larangan bagi pengurus harian NU memiliki rangkap jabatan sebagai pengurus harian partai politik/organisasi sosial politik mana pun.
Muktamnar Situbondo. Sumber: YouTube
Materi keputusan itu, menurut A. Gafar Karim dalam Metamorfosis, NU dan Politisasi Islam Indonesia (1995), dianggap penting sehingga pada 26 Oktober 1985, PB-NU kembali menegaskan pelarangan rangkap jabatan dengan SK 72/A-II/O4-d/XI/8587 dan No.92/1986.
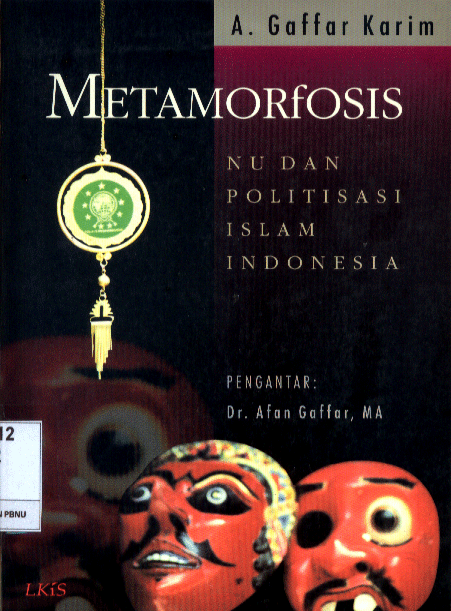
Metamofosis NU. Sumber: Nahdlatul ulama
Instruksi semacam ini tentu dirasakan sebagai suatu hal yang kurang mengenakkan bagi sebagian pemimpin-pemimpin di daerah-daerah, karena para pengurus NU di daerah-daerah kebanyakan juga menjabat sebagai pengurus PPP. “Dihadapkan pilihan seperti itu, sebagian dari mereka mematuhi instruksi tersebut dengan menanggalkan jabatannya di PPP, namun juga ada yang menolak,” tulis Gafar.
Bila prinsip netralitas NU terhadap partai-partai politik sebagai konskuensi kembali ke khittah 1926 benar-benar dijalankan seperti keluarnya instruksi itu, mau dikemanakan massa NU yang besar dan relatif kohesif itu? Menjelang diselenggarakannya kampanye Pemilu 1987, jawaban terhadap pertanyaan itu mulai menampakkan kejelasan.
Telur Busuk
Para pemimpin NU, termasuk Gus Dur, semakin terlihat aktif melakukan perjalanan ke daerah memberikan pengarahan warga NU. Intinya, mereka membawa pesan sederhana, warga NU tidak lagi wajib memilih PPP, tidak haram mencoblos Golkar dan PDI. Tetapi dalam penyampaian mereka memiliki titik tekan berbeda-beda, yang itu tergantung pada kepentingan yang melatarbelakanginya.

Sumber: nutegalkab
Bagi para tokoh NU yang semula di PPP kemudian disingkirkan Ketua Umum PPP Jhon Naro, seperti Yusuf Hasyim, Mahbub Junaidi dan seterusnya, pesan-pesan yang disampaikan sarat dengan muatan sentimen terhadap PPP.
Bagi mereka yang merasa akan mendapatkan keuntungan bila suara NU berpindah ke Golkar, namun tidak pernah terlibat langsung konflik dengan Naro, umumnya melakukan persuasi lebih halus agar massa NU mengalihkan suaranya ke partai pemerintah.
Namun, di samping tokoh-tokoh yang menggunakan khittah dengan muatan-muatan kepentingan itu, banyak juga tokoh-tokoh NU yang melakukannya dengan tulus demi kebaikan organisasi. Upaya-upaya tokoh-tokoh NU agar warganya meninggalkan dukungannya pada PPP dalam Pemilu 1987 itulah yang kemudian diistilahkan “penggembosan”.
Gerakan penggembosan yang tampaknya secara diam-diam menjadi policy kepemimpinan Gus Dur menjadi sangat efektif karena diperburuk oleh pernyataan-pernyataan provokatif J. Naro sendiri yang menjelek-jelekkan NU. Di berbagai kesempatan, Naro mengatakan mereka yang meninggalkan partai sebagai “telur busuk” yang jumlahnya tak lebih 200 ribu orang.
Syamsuddin Haris dalam PPP dan Politik Orde Baru (1991) menyebut, Naro berpidato di hadapan massa PPP Bandung, berujar sangat kasar: ”biar saja telur busuk itu keluar dari partai. Terlalu lama dalam keranjang (PPP) yang baik ini malah akan merusakkan telur-telur lain yang masih bagus.”
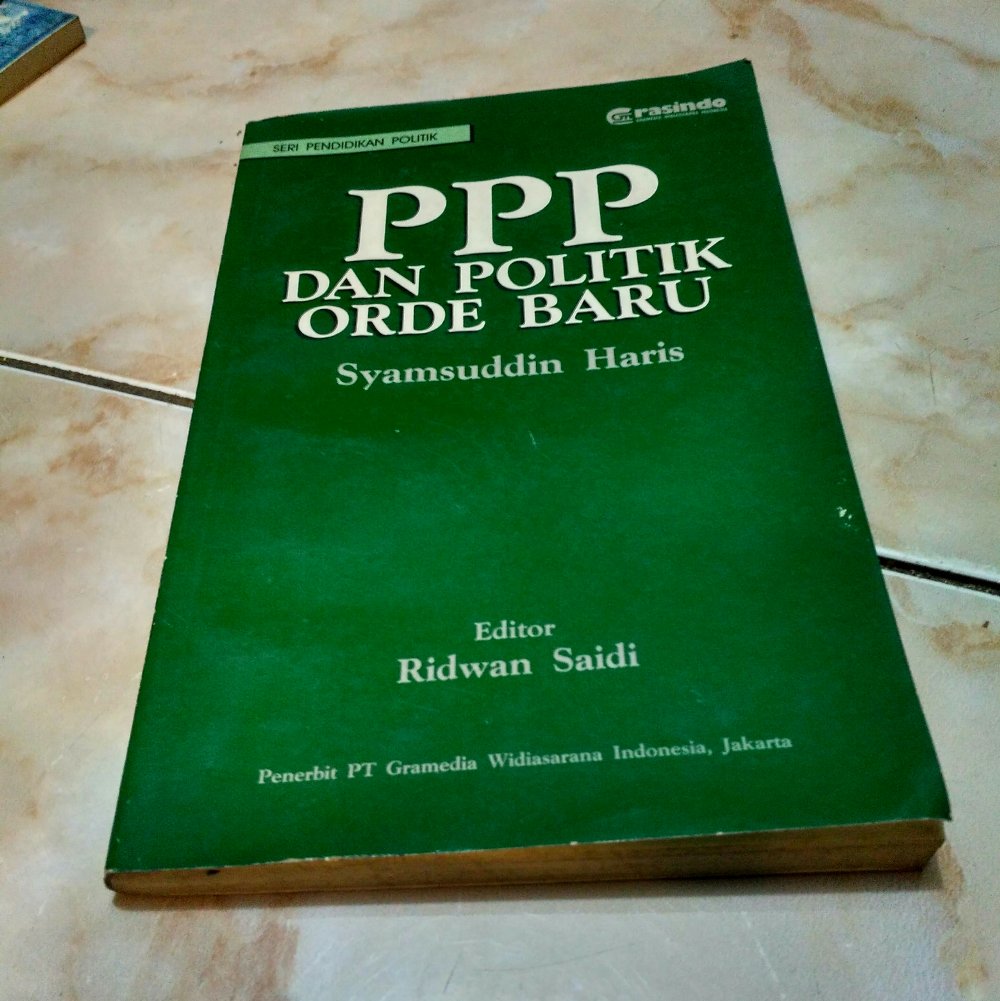
PPP-Politik Orba. Sumber: bukalapak
Pernyataan-pernyataan vulgar semacam itu tentu semakin menyulut emosi di kalangan tokoh-tokoh dan warga NU. Senjata ampuh lain yang digunakan untuk mengempiskan suara PPP adalah isu asas tunggal yang berarti PPP tidak lagi bisa mengklaim sebagai partai Islam.
Adalah para tokoh-tokoh NU berpengaruh seperti Kiai Fuad Hasyim (Cirebon), Kiai Hamid Baidhowi (Lasem), Kiai Syafi’i Sulaiman, Kiai Shohib Bisri, Kiai Yusuf Hasyim, Saiful Mujab dan Mahbub Junaedi yang paling aktif berkeliling keliling ke daerah-daerah untuk melakukan penggembosan.
Para tokoh-tokoh tersebut biasanya menggunakan acara-acara ceramah keagamaan (pengajian) sebagai ajang pengggembosan sehingga kadang sulit dibedakan apakah itu acara pengajian atau penggembosan. Semakin mendekati Pemilu, para tokoh NU terlihat semakin intensif menggerogoti PPP sehingga di Jawa Timur saja tak kurang dari 900 pengajian yang dimuati pesan “pemboikotan” pada PPP.
Mereka, baik secara terang-terangan atau implisit, membujuk warga NU untuk memilih Golkar. Sekurang-kurangnya para tokoh NU dalam materi-materi ceramahnya menegaskan berulang-ulang garis batas NU dan PPP dibandingkan dua OPP yang lain terutama Golkar.

GusDur.Sumber: Adib Susula Siraj Dua
Rentang waktu massa kampanye, Gus Dur kerap mengisi acara-acara “pengajian” di Golkar. Di Surabaya, Gus Dur memberikan ceramah di DPD Golkar Jawa Timur, ketika pada hari yang sama PPP juga menggelar kampanye. Dalam konteks acara yang sama, Gus Dur berbicara dalam acara Isra Mikraj di Gedung DPP Golkar di Jakarta.
Pada Harlah NU ke-61 di Surabaya, di hadapan sekitar 10.000 warga Nahdhiyah Gus Dur mensinyalir adanya kesalahpahaman hubungan umat Islam dan negara yang sering diwarnai pertentangan. Gus Dur dalam acara itu berkali-kali menyatakan, NU secara kelembagaan telah meninggalkan politik praktis.
Ia juga aktif melakukan kontak-kontak lobi dengan pimpinan Golkar, yang bisa ditafsirkan sebagai suatu konsesi politik dijanjikan akan diberikan oleh Golkar kepada pemimpin NU itu bila berhasil mengkonversikan pengikutnya ke Golkar berhasil.
Atas dasar itu, dalam retrospeksi, Gus Dur seringkali dianggap bertanggung jawab dalam gerakan penggembosan ini. Pengritik yang paling vokal terhadap aksi penggembosan itu adalah K. H. Syansuri Badawi, seorang guru senior di Tebuireng dan calon PPP di DPR.
Dalam sebuah serangan yang tersebar luas terhadap Gus Dur dan pendukungnya, dia menyatakan bahwa sebagai umat Islam, warga NU tidak punya pilihan kecuali memberikan suaranya kepada partai Islam, PPP.
Martin Van Bruinissen dalam NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wanaca Baru (1994) menyebut, umat Islam luar NU yang taat, termasuk banyak di antaranya yang memandang rendah kepemimpinan Naro, melontarkan cemooh yang bertubi-tubi kepada Gus Dur karena dipandang mengkhianati kepentingan Islam. Apa pun tuduhan yang ditujukan pada Gus Dur, gerakan penggembosan ini tampaknya merupakan langkah lanjut “pembaru muda” untuk melakukan “eksperimen politik strategi akomodasi berprinsip” dengan negara.
Beberapa tokoh NU, di antaranya K. H. Syafi’i Sulaiman yang terkenal dengan interplasi NKK/BKK-nya itu, memiliki alasan kenapa penggembosan itu perlu dilakukan. “Tapi pemerintah tidak percaya bahwa NU betul-betul netral dari PPP. Sebab, Imam Sofwan, Imron Rosadi masih di PPP. Untuk membuktikannya bahwa NU betul-betul keluar dari PPP suara P3 harus dikurangi. Tanpa itu pemerintah tidak percaya kepada NU. Pemilu ini merupakan transisi.”
Betapa pun usaha-usaha membendung gelombang penggembosan telah dilakukan PPP, termasuk tokoh NU yang masih berada di partai itu, upaya itu sia-sia belaka. Selebaran-selebaran yang beredar di kalangan NU sangat merugikan PPP. Demikian halnya dengan kajian-kajian keagamaan yang dilakukan tokoh-tokoh NU yang lebih banyak memberi angin pada Golkar.
Derasnya gelombang penggembosan yang dilakukan tokoh NU menjelang Pemilu keempat Orde Baru itu benar-benar membuat kelabakan para aktivis PPP. Dilaporkan, banyak DPC PPP mengeluhkan sulitnya mencari saksi pemungutan suara dan Panwaslakcam.
Kampanye-kampanye partai berlambang bintang tersebut juga sepi dari pengunjung. Sebagian pemimpin NU Jawa Timur, menurut Martin Van Bruinessen, malah terlibat berlebihan dalam menyerang PPP, sehingga memunculkan ketegangan sosial di beberapa tempat.
Suatu hal yang dianggap melampui proporsi yang diharapkan pemerintah. Oleh karena itu, Laksusda (aparat militer) yang elitnya kebetulan terlibat rivalitas dengan pimpinan Golkar segera mengeluarkan larangan berceramah beberapa tokoh NU. Meskipun kemudian Ditsospol mencabut kembali “pencekalan” terhadap tokoh NU yang “menghantam” PPP melalui ceramah-ceramahnya.
Yang menarik, alasan yang dipakai dalam “penggiringan” massa NU ke Golkar antara lain adalah, meningkatnya sarana-sarana ibadah umat Islam berkat bantuan pemerintah. Suatu bahtsul-masail yang diadakan pondok-pondok pesantren se-DI Yogyakarta, menurut Kacung Marijan berkesimpulan:
“Apabila pertimbangan-pertimbangan di atas diterapkan dengan kritis dan tidak emosional, Golkarlah yang pantas dipilih dalam Pemilu, sebab kecuali telah membawa manfaat bangsa dan umat Islam Indonesia, kita juga lebih dapat mengamalkan taat kepada Ulil Amri dan dapat lebih dekat lagi dengan…jadi memilih Golkar adalah pilihan yang tepat. Kami yakin, dengan menitipkan aspirasi melalui Golkar, di samping kita ikut menjaga kewibawaan ulama, juga pemasyarakatan ajaran ahlussunah wal jamaah akan lebih dapat terealisir.
Koalisi de facto NU dengan bekas “musuh besarnya,” Golkar, menghasilkan suatu perolehan suara yang mengejutkan dalam Pemilu 1987. Golkar mengalami lonjakan suara yang cukup besar, dari 64,34% pada Pemilu 1982 menjadi 72,99% pada Pemilu 1987. Sementara PPP hanya memperoleh 15,96%, yang berarti mengalami penurunan 11,82% dibandingkan Pemilu sebelumnya. Di daerah-daerah kantong-kantong NU, PPP mengalami kemerosotan suara yang besar, sebaliknya perolehan suara Golkar semakin menggelembung.
Terhadap dinamika baru hubungan NU dan Golkar selama Pemilu 1987 tersebut, William Liddle memberikan kesimpulannya: “kekalahan PPP karenanya merupakan kemenangan NU. Pemimpin NU memberikan suara kepada Golkar dan dengan demikian meningkatnya pengaruhnya dalam sistem politik. Secara organisasional, otonomi NU semakin kuat. Sekolah-sekolah dan guru-gurunya sekarang menjadi sasaran sumbangan pemerintah, bukan permusuhan. Beberapa anggotanya berpengaruh di dalam Golkar, dan akan diberi posisi pimpinan untuk menjadi perekat persekutuan de facto itu. Yang terpenting, dalam menggembosi suara PPP hampir setengahnya, NU mempertontonkan kekuatan massanya dengan cara istimewa dramatis. Hasil akhimya walaupun tentunya terlalu awal untuk menarik kesimpulan ketat dan penampilan NU merupakan sebagian saja dari komunitas santri, mungkin adalah akomodasi baru antara dua tradisi budaya besar Indonesia”.
Sebagai konsesi atas penyeberangan massa NU ke Golkar dalam Pemilu 1987, Gus Dur dan Saiful Mujab (mantan politisi PPP), menurut Syamsuddin Haris, memperoleh kursi MPR-RI dari FKP. Beberapa tokoh NU lain yang menjadi anggota MPR yang ditunjuk pemerintah adalah K. H. Imron Hamzah (mantan anggota DPR dari PPP) dan H. M. Syahmanaf (mantan fungsionaris PPP DKI Jakarta).
Lebih jauh lagi, dalam SU MPR itu Gus Dur melakukan lompatan akomodasi politik yang “spektakuler”, dengan kesediaannya menyetujui status aliran kepercayaan dalam GBHN sebagaimana yang dikehendaki oleh kelompok kebatinan di Golkar.
Langkah ini jelas sangat berlawanan dengan sikap politik para ulama dan pemimpin NU yang dalam SU MPR 1978 melakukan walk out atas kedudukan aliran kepercayaan dalam GBHN. Namun usaha NU untuk memasukkan pesantren ke dalam GBHN tidak berhasil karena kurang mendapatkan dukungan fraksi-fraksi pemerintah. Tetapi, yang terpenting dari kehadiran pimpinan NU di MPR mewakili FKP dan kesediaannya dalam menyetujui keberadaan aliran kepercayaan dalam GBHN itu adalah makna simbolis bagi suatu tahap pembalikan dari periode sebelumnya.
Bila periode dua dasawarsa pertama Orde Baru organisasi Islam terbesar ini berada dalam garda depan kekuatan politik Islam yang “oposan” terhadap negara, pada awal kepemimpinan Gus Dur justru berubah sikap menjadi altermatif terhadap aksentuasi politik negara Orde Baru.