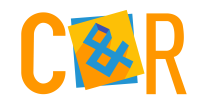Kritik Film Trilogi I – Will – Survive
Ceknricek.com–Bapak perfilman Indonesia, Usmar Ismail, pernah membuat kredo yang terkenal,”…Seorang seniman Indonesia akan tetap menjadi personifikasi hati nurani rakyat yang rindu akan kemerdekaan, keadilan dan kemakmuran lahir batin, dan dia akan tetap menentang setiap kezaliman baik mental dan fisik, jika dia merasakan secara intens denyut jantung rakyat, jika dia memasang jiwanya sebagai layar-radar yang menanggapi kejadian yang berlangsung di sekitarnya.” Dengan kata lain, seniman, tentu termasuk sineas, harus peka terhadap peristiwa, fenomena dan tuntutan yang terjadi di tengah masyarakat. Seniman mirip pipa saluran untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.Sutradara, sebagai salah satu kreator utama di karya film, jika tidak mau hanya memamah biak dan mereproduksi karya yang sudah selalu didaur ulang, tidak dapat mengelak dari tuntutan seperti ini.
Pemikiran Usmar Ismail itu sejalan dengan pendapat Sigfreid Kracauer yang menegaskan, film suatu bangsa mencerminkan mentalitas bangsa itu lebih dari media artistik apapun (From Caligari to Hitler: A Psychological History of the German Film: 1974). Meski dengan cara menguraikan yang berbeda, tetapi Arnold Hauser berpendapat sama pula. Menurut dia, bahasa kesenian adalah hasil dari sebuah proses dialektika yang bertolak dari idiom nasional dalam usaha dan perjalanannya menjadi suatu karya yang universial (The Sociology of Art: 1982). Bertitik tolak dari peristiwa-peristiwa nyata sehari-hari yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia, sutradara Anggy Umbara, membuat sekaligus film trilogi yang berjudul I, Will dan Survive. Sebagai film trilogi sebenarnya masing-masing mempunyai judul terpisah,tetapi dapat juga dibaca menjadi satu I Will Survive. Film ini ditayangkan di media over the top(OOT) atau streaming, sejak medio Juli tahun ini. Ketiga film ini dapat dibedakan satu dengan lainnya, tetapi tidak dapat dipisahkan, karena memiliki benang merah yang kuat. Bagaikan rumah, masing-masing memiliki ruangan sendiri-sendiri yang terpisah, namun tetap satu kesatuan sebagai rumah.
Hilangnya Empati
Lewat film ini Anggy mengaku ingin merefleksikan keadaan masyarakat. Apa itu? Masyarakat kita kini sedang mengalami tata nilai yang kacau balau. Hukum dan keadilan sering hanya menjadi pajangan yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Rasa keadilan tidak lagi diukur dari detak jantung kehidupan masyarakat, tetapi dari balik hukum formal yang sering lambat, mahal dan tetap tidak adil. Hal ini mendorong banyak pihak menjadi frustasi dengan proses hukum, dan memunculkan dendam yang akhirnya memilih mencari keadilan dengan jalan sendiri.
Apalagi lingkungan sosiologis masyarakat mendukung ke arah itu. Sudah jamak kita mendengar dan melihat banyak pembunuhan dilakukan secara sadis, baik karena menerima bayaran maupun karena persoalan sepele. Lebih parah lagi, sebagian kejahatan itu dewasa ini dilakukan oleh para remaja bau kencur. Mereka tega membunuh dan memperkosa beramai-ramai. Anak-anak itu manakala melakukan kejahatan seperti sudah kehilangan rasa kemanusiaannya. Para anak kini membunuh dengan rasa nikmat. Tak ada empati sama sekali terhadap para korbannya, suatu rasa yang antara lain membedakan manusia dari mahluk lainnya.
Anak-anak yang seharusnya masih polos dan senang bermain-main, sudah menjadi pembunuh berdarah dingin. Selain belajar dari lingkungan, mereka juga belajar dari keluarganya sendiri, terutama dari orang tuanya. Perilaku orang tua dapat dicontoh langsung, ataupun karena perbuatan orang tua yang memiliki dampak psikologi yang menyakitkan anak secara dalam. Dalam keadaan seperti ini, jika ada triggle atau pemicunya, para anak-anak itu akan berkembang menjadi seorang psikopat. Sekarang pun, sesungguhnya, Anggy melihat sudah banyak psikopat walaupun belum diberi label penyimpangan jiwa itu. Bagi Anggy peran orang tua memberikan pendidikan yang baik kepada anak, bukan saja supaya anak itu tumbuh dengan rasa kemanusiaan, tetapi sekaligus juga untuk menjaga peradaban manusia.
Akumulasi Kekecewaan
Pada film I, yang sebelumnya berjudul Petrus, sang tokoh utama Sandjaya (Omar Daniel), kehilangan Mila (Amanda Rigby), isterinya, entah kemana. Setelah enam bulan, polisi yang dilaporkan kasus ini, sama sekali belum berhasil menemukan titik terang. Akumulasi kekecewaan atas hilangnya isterinya, menyebabkan perasaan keadilan dirinya terkoyak-koyak, membuat Sanjaya ingin menunjukan dirinya juga dapat ikut menegakkan keadilan melalui caranya sendiri. Prinsipnya, “aku ada karena aku mampu memberantas ketidakadilan”. Unsur aku, atau “I, ” menjadi sangat menonjol.
Sedangkan pada film berjudul Will, yang semula berjudul Broken, mengisahkan Andra (Morgan Oey) sedang mengalami hubungan yang kompleks dengan isterinya, Vina (Anggika Bolsteri). Apalagi anak mereka satu-satunya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Untuk mengurangi rasa stress, Andra bersepeda kehutan yang berbukit-bukit, namun karena banyak pikiran dia tidak fokus, dia terjatuh. Terguling. Patah tulang. Tidak ada orang lain yang melihatnya, apalagi dapat menolongnya. Dalam keadaan demikian, hidup atau mati tergantung hasrat diri atau keinginan diri sendiri. Will dia. Kalau tidak memiliki will akan tamatlah riwayatnya.
Ada pun film Survive,yang semula berjudul Obey, membeberkan siapa sebenarnya diri Dani (Onandio Leonardo). Sewaktu kecil dia melihat Ayahnya selalu menyiksa ibu tirinya. Salah sedikit ibu tirinya dihajar. Dani juga mengintip perlakuan kasar seksual Ayahnya terhadap sang ibu tiri. Bahkan Dani diajarkan oleh ayahnya tidak boleh lemah terhadap wanita. Jiwa Dani tergoncang. Dia tumbuh menjadi seorang pembenci wanita yang selingkuh, dan pada akhirnya Dani tumbuh menjadi seorang psikopat. Dia menyiksa para korbannya. Sedangkan para korban Dani mencoba bertahan terhadap segala siksaan dari Dani. Mereka mencoba untuk survive…
Genre Thriller Gore
Di dunia sudah amat banyak film genre thriller yang berkisah tentang psikopat. Salah satu yang terkenal film The Silince of The Lambs karya sutradara Jonathan Demme yang dibuat tahun 1991. Sebelumnya ada juga film tentang psikopat yang lebih sadis, Halloween (1978) karya sutradara David Gordon Greeen dan sebagainya.Di Indonesia sendiri kisah tentang psikopat pernah beberapa kali diangkat, antara lain Fiksi karya Mouly Surya (2008) dan Love and Edeleiss Karya Anto Tandjung (2010). Artinya baik di dunia maupun di Indonesia film genre thriller sudah banyak. Bukan barang baru.
Bedanya dengan film psikopat Indonesia lainnya, semua film-film itu berjudul tunggal, sedangkan karya Anggy merupakan trilogi. Pada film lain lebih banyak fokus kepada persoalan individual, pada I – Will – Survive merujuk kepada sebab musabab sosial. Begitu pula kalau yang lain fokus pada individu yang ada di tiap film, pada I – Will – Survive dari masing-masing tiga film juga mempunyai tokoh tersendiri, tetapi mereka mempunyai hubungan. Selain itu, film ini genre thrillernya dari sub genre gore, thriller yang penuh sadis dan berdarah-darah.
Lihatlah adegan ayah Dani dengan santai mencincang tubuh isterinya . Darah muncrat kemana-mana. Dia dengan tenang menaruh salah satu jari isteri ke kantong baju. Belajar dari Bapaknya, Dani ketika besar seperti mengalami de javu.Dani mengulang lagi yang dilakukan ayahnya, mencincang-cincang korban Mila bagaikan memotong daging sapi korban. Dia menikmati benar memotong-motong tubuh manusia dengan darah yang muncrat kemana-mana. Sama tepat waktu bapaknya melakukan hal serupa. Dia seakan mendapat dukungan darah Ayahnya.
Pendekatan Semiotika
Seni bukan cuma soal apa yang ingin disampaikan, melainkan juga bagaimana cara menyampaikan pesannya itu. Bagaimana menangkap dan memahami sebuah film, antara lain,dapat melalui pendekatan semiotika yang dikembangkan oleh Ferdimand Sauussure dan Charles Sanders Peirce pada abad ke delapan belas. Waktu itu semiotika masih diartikan sebagai ilmu tentang tanda. Dalam perkembangannya kemudian, pemaknaan semiotika pada zaman “modern” meluas menjadi semiotika yang berkaitan dengan kebudayaan dan sosial termasuk karya-karya seni sebagaimana dijelaskan oleh Umber Eco (A Theory of Semiotics: 1979) dan Ronald Barthes (Element of Semiology: 1988). Dalam film, tanda harus dibaca sebagai bahasa gambar dengan seperangkat pendukungnya seperti visual, editing, gerak kamera, shot-shot, suara, cerita, imaji dan hubungannya masing-masing, yang kemudian secara kesatuan sering disebut konsep sinematografis. Maka menurut James Manaco, semiotika dalam film sudah bersifat otonom dan kompleks (How to Understaning A Film:1977).
Dari uraian itu, tegasnya dalam menilai film haruslah dengan pendekatan ilmu film itu sendiri, termasuk relasinya dengan penonton. Walaupun film merupakan pemberontakan terhadap “rasa” sehingga dapat menjadi “liar” tetapi pemahaman terhadap film tetap harus dalam koridor semiotika film sendiri, sehingga ada sekumpulan parameternya. Misalnya pemikiran awal film Bela Balaz menyebut karena film memiliki prinsip kemanusiaan,maka dia menempatkan perspektif manusia sebagai pusat dari alam semesta melalui penggunaan close up (Theory of The Film: Character And Growth A New Art: 1952). Lewat close up objek menjadi terlihat jauh lebih besar dan detail di layar, dan itu bagi Bela Balaz menunjukkan sesuatu yang penting dari objek itu dalam relasi kemanusiaan.
Bagaimana penerapan semiotika dalam film I – Will – Survive? Anggy Umbara memandang tabiat-tabiat eksplosif manusia, termasuk psikopat, karena hati mereka terkoyak, dan mereka berada dalam kukungan kesepian, meski di tengah keramaian sekalipun. Padahal sepi itu kejam. Oleh karena itu Anggy lebih banyak memilih penggambaran yang menempatkan objek dalam posisi yang kecil dalam gambar yang besar. Sandjaya di atas gedung yang luas di tengah kota, diambil dari atas, terlihat kecil. Dia menjadi seperti hampir tak berarti.
Banyak adegan lain serupa itu. Sandjaya di atas meja makan,juga sendiri. Kesepian. Demikian pula Andra sendiri di tengah hutan. Sepi sendiri. Para korban Dani yang diikat di tempat tidur, di ruangan yang kosong, sama juga, sendiri . Penampakan objek yang kecil dalam gambar besar, secara semiotika memberi makna kesepiannya para objek itu.
Sedangkan untuk menunjukan kegelisahan para tokohnya, kamera diambil secara bergerak, bukan statik. Dengan begitu kegelisahan para tokoh terpancar dari gambar yang disuguhkan.
Adapun topeng-topeng yang dikenakan Dani, dimanfaatkan sebagai perlambang kepalsuan atau kemunafikan. Macam-macam topeng menunjukan ada macam-macam kepalsuan. Selama korbannya masih belum membongkar kepalsuan, selama itu pula topeng akan ada pada dirinya. Barulah setelah ada pengakuan mengenai kesalahan mereka, topeng dibuka.
Adapun pilihan genre thriller gore, dengan banyak kata-kata kotor yang terlontar dari mulut pelaku, Anggy ingin menunjukan memang itulah yang terjadi di tengah masyarakat. Banyak sadisme di masyarakat. Berita dari televisi bukan saja untuk memberikan informasi dalam film, tetapi sekaligus juga menunjukkan dari mana inspirasi Anggy berasal. Di luar itu, kekerasan, sadisme dan darah merupakan cara Anggy ingin menarik orang menonton filmnya.
Catatan Pinggir
Anggy Umbara merupakan seorang sutradara yang sudah sangat berpengalaman. Dia sudah menangani berbagai genre film. Dia juga sudah biasa menghasilkan film-film yang meraih banyak penonton. Dengan begitu, kemampuan teknikal dan instink filmnya tak perlu diragukan lagi. Kendati begitu dalam film I – Will – Survive ada beberapa catatan pinggir yang perlu diperhatikan.
Pertama-tama, menjadi pertanyaan, bagaimana Dani dapat merawat rumah sebesar miliknya, dan tetap bersih, tanpa seorang pun pembantu? Mungkin saja dia memakai jasa cleaning service, atau memakai asisten rumah tangga yang pulang, tapi sama sekali tak ada informasi tentang itu.
Memang film memiliki proposi-proposi yang independen terhadap realitas, tetapi logika berpikir tetap tak dapat diabaikan.Unsur sosiologis dari sebuah lingkungan perlu juga diperhatikan dalam menyajikan gambar. Di Barat, orang tinggal sendirian diapartemen sudah biasa,tetapi di Indonesia di rumah yang relatif kecil saja, ada pembantu, sehingga penjelasan kecil soal ini menjadi sangat perlu.Planning information diberikan dengan baik sewaktu Sandjaya belajar menembak kepada ayahnya. Dengan demikian, waktu dia mahir menembak, tak perlu lagi ditanyakan bagaimana dia dapat mahir menembak. Begitu juga kenapa Andra main sepeda ke hutan , sudah diberikan informasi awal, sehingga tidak lagi menimbulkan tanda tanya. Aksen dari Ayah dan Dani yang berasal dari daerah tertentu, tanpa bermaksud menghina suku tersebut, juga menjadi informasi yang bermanfaat bahwa peristiwa ini terjadi di bumi Indonesia.
Sebagai catatan pinggir berikutnya, biasanya seorang psikopat merupakan orang yang cerdas, cermat dan berhati dingin. Dia sudah memperhitungkan segala kemungkinan dengan detil. Sebelum menculik dan mengurung orang di kamar rahasia, seharusnya Dani sebagai orang terkena gangguan jiwa psikopat, sudah memperhitungkan kemungkinan korbannya akan meronta dan berteriak-teriak. Dia sepatutnya mengukur sampai seberapa jauh daya teriakan para korbannya akan menembus tembok pemisah antara rumah utama dan ruang-ruang rahasia. Kendati dapat saja berdalih, kan di rumahnya tidak ada orang, seorang psikopat tidak ada berspekulasi membiarkan suara teriakan korbannya atau suara barang-barang dapat terdengar ke sebelah.
Demikian juga pilihan tempat menembak Sandjaya terakhir kali dapat menimbulkan pertanyaan. Sebelumnya, dia menembak dari jarak jauh, sehingga tidak dapat dipantau oleh para korbannya. Namun pada penembakan yang terakhir, dia justeru melakukannya dari jarak relatif dekat, padahal dia mengetahui korbannya sedang dijaga oleh para pengawalnya. Pilihan tempat yang dekat terlalu beresiko untuk dapat diketahui, dan lebih parah lagi, dapat diserang balik. Itulah yang kemudian terjadi. Kita bertanya-tanya, kenapa Sandjaya tiba-tiba menjadi begitu gegabah? Kalau untuk membuat dia terluka barangkali dapat dicari sebab lain yang lebih logis.
Catatan lain yang perlu mendapat perhatian, hubungan antara Sandjaya dengan ayahnya, selama film terkesan cukup tegang. Tak ada informasi si ayah mengetahui aktivitas Sandjaya. Demikian juga tak ada informasi keluarga tersebut mempunyai senapan dua. Satu senapan selama ini dipakai Sandjaya untuk memburu korban-korbannya. Dari mana ayah Sandjaya memperoleh senjata dalam waktu begitu cepat? Begitu pula menjadi pertanyaan, dari mana ayahnya tahu rumah Dani apalagi sampai sudah lengkap membawa senjata ?
Sebaliknya adegan penculikan Vina ketika diletakan di penggalan terakhir Will justeru menjadi informasi yang terlalu cepat. Dengan pemaparan ini, cerita menjadi lebih mudah ditebak dan mengurangi unsur surprise. Mungkin lebih baik jika adegan penculikan itu ditempatkan juga di bagian Survive, sehinga penonton lebih surprise. Boleh jadi penculikan itu dimaksud sebagai”jembatan” atau benang merah untuk film-film lainnya, tetapi ada cara lain untuk itu, tanpa membocorkan lebih dahulu adegan itu. Kalaulah adegan itu diletakan di bagian Survive sebagai film thriller, akan lebih menarik tanpa penonton kehilangan benang merah itu.
Terlepas dari catatan pinggir ini , Anggy sudah menghasilkan film trilogi yang satu sama lain berbeda karakternya, dan dia telah dapat memenuhi kaedah semiotika dengan baik. Anggy telah berhasil memantulkan yang terjadi di lingkungan ke layar putih. Setidaknya Anggy sudah seperti yang dikatakan Usmar Ismail, ”…Seorang seniman Indonesia akan tetap menjadi personifikasi hati nurani rakyat yang rindu akan kemerdekaan, keadilan dan kemakmuran lahir batin, dan dia akan tetap menentang setiap kezaliman baik mental dan fisik, jika dia merasakan secara intens denyut jantung rakyat, jika dia memasang jiwanya sebagai layar-radar yang menanggapi kejadian yang berlangsung di sekitarnya.”
Anggy sudah memasang layar-radar menjadi seniman Indonesia yang menjadi personifikasi rakyat dan merasakan denyut rakyat dengan menanggapi kejadian yang berlangsung di sekitarnya.***