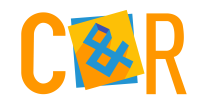Ceknricek.com–Hubungan kedekatan rezim Jokowi dan China, serta dampaknya pada Islamophobia di Indonesia, dapat kita perkirakan berasal dari paham Komunisme rezim Tiongkok. RRC ini, meskipun mereka menjalankan ekonomi kapitalistik, saat ini, mereka tetap saja meyakini doktrin Komunis dan kepemimpinan otoriter dalam politik negaranya. Korban kekejaman rezim Komunis ini, di RRC, dapat kita lihat dari pembantaian etnis Islam secara massif di Uighur, XinJiang. Selain itu, Islam dipandang sebagai peradaban yang harus dihilangkan dalam pentas politik nasional, agar kedekatan China dan Indonesia dapat bertahan lama. Sebab, tragedi di masa lalu, seperti kasus G30S/PKI, China kehilangan persahabatan dengan Indonesia, setelah umat Islam Indonesia bersekutu dengan militer dan barat dalam melawan pengaruh Komunis. Dugaan yang lebih sederhana adalah rezim Peking lebih merasa efisien berhubungan dengan Indonesia melalui penggalangan kelompok etnis Cina Konglomerat, dengan membangun oligarki, dan menguasai Indonesia dalam jangka Panjang. Kita mengetahui bahwa segelintir oligarki kita mempunyai loyalitas ganda, khususnya ketika diperlihatkan oleh banyaknya uang-uang Indonesia yang disimpan di Singapura atau luar negeri lainnya, dan seorang diantaranya viral mengaku bahwa “Cina adalah ‘ayah kandung’ mereka, seang Indonesia ayah tiri”. Sebaliknya, Islam, di mata Peking dan pendukungnya, umumnya kaum minoritas, adalah ancaman bagi eksistensi negara sekuler Indonesia.
Beban dan ancaman yang demikian berat yang dialami umat Islam Indonesia oleh rezim Jokowi, terutama pada kasus pembunuhan yang melanggar hukum (Unlawfull Killing) pada 6 pemuda anggota laskar FPI di KM 50 akhir Desember 21, pemenjaraan Habib Rizieq dkk., penembakan atas demonstran pada aksi 21-22 Mei 2019, dan lain sebagainya, telah mengantarkan berbagai ormas Islam menggalang kekuatan anti Islamophobia di era Jokowi. Banyak orang bertanya, bukankah isu anti Islamophobia itu tepatnya hanya eksis di mana muslim sebagai minoritas? Namun, faktanya, Indonesia yang mayoritas muslim dikendalikan elit yang tidak bersahabat dengan Islam, sebagai sebuah ajaran peradaban, yang diakui oleh ideologi bangsanya, Pancasila.
Tragedi paling terakhir ini, yakni kasus Ferdi Sambo, di mana polisi telah diidentikkan dengan sarang mafia, yang minim moralitas, menunjukkan instrument penindak lawan-lawan politik Jokowi itu, memang berada pada posisi yang sangat diametral berlawanan dengan peradaban Islami. Merujuk pada kematian polisi ini, di mana mereka sangat dominan sebelum kasus Ferdy Sambo, tentu saja kebiadaban polisi pada ulama dapat dimengerti. Bagaimana membayangkan sebuah negara yang menganut demokrasi, memenjarakan ulama besar Habib Rizieq selama dua tahun di penjara bawah tanah? Untuk kesalahan yang tidak jelas. Sekali lagi ini lah bentuk Islamophobia akut.
Model Pembelahan Sosial di Era Digital dan Islamophobia
Dalam dimensi sosiologis, masyarakat Indonesia disebutkan antropolog Amerika Clifford Gerz mempunyai keterbelahan sebagai berikut, pertama masyarakat dengan kultur santri, kedua, dengan kultur abangan dan ketiga kultur priyayi. Santri merujuk pada ketaatan terhadap agama Islam. Abangan merujuk pada kultur animisme. Sedangkan priyayi merujuk pada aspek Hindu, yang eksis di Kraton. Dhuroruddin Mashad, dalam buku “Politik Kaum Santri dan Abangan”, 2021, menggunakan pembelahan ala Clifford Gerz sebagai awal kajian. Selanjutnya , dia memperinci pengelompokan yang lebih terbelah antara santri perkotaan dan pedesaan. Pembelahan merujuk komitmen pada Islam, terjadi versus antara santri dan abangan. Pada pembelahan merujuk agama ini, Mashad memasukkan kaum priyayi pada kelompok abangan juga, namun, memberi catatan bahwa, secara kultural, priyayi yang mengalami pendidikan barat, sehingga keterlibatan mereka pada moral elit terjadi. Priyayi dalam ruang publik menjaga etika sosial, sebaliknya kaum abangan kelas bawah, merupakan masyarakat yang terbuka pada praktik anti agama, seperti sabung ayam, pelacuran, dukun, dll. Sehingga dalam kelompok abangan, Mashad membagi abangan dalam abangan sekularisme (kaum priyayi) dan abangan marginalis.
Keempat sub kultur pembentuk identitas masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa, telah membawa para ahli meyakini bahwa pembentukan partai politik di antara mereka sesuai mewakili aspirasi sub-kultur mereka tersebut, di awal kemerdekaan, seperti santri modernis membentuk Masyumi, santri tradisionalis membentuk partai NU, abangan sekuleris membentuk PNI (Partai Nasional Indonesia) dan abangan marginalis membentuk PKI (Partai Komunis Indonesia). Namun, tantangan demi tantangan perjalanan bangsa menunjukkan pembelahan tersebut bersifat dinamis, misalnya, ada kalanya kerjasama dan konflik yang dalam terjadi tidak mengikuti kemungkinan logik yang seharusnya. Misalnya, Ketika awal kemerdekaan kelompok santri, baik tradisional maupun modern, keduanya sepakat Islam dijadikan ideologi negara. Namun, hal itu tidak pernah terjadi lagi setelahnya. Meskipun, semua kelompok santri percaya bahwa dalam Islam tidak dapat dipisahkan antara agama dan politik. Sebaliknya juga terjadi di kalangan abangan, ketika awal kemerdekaan, berkali-kali diperlihatkan konflik antara kelompok Komunis dengan Nasionalis.(Bersambung)
(Paper Dr. H. Syahganda Nainggolan, MT, dalam Kongres Umat Islam Sumut ke- 2, di Asrama Haji Medan)