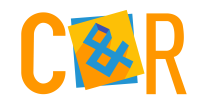Ceknricek.com — Siapa pun berhak menyikapi situasi politik yang kini sedang berlangsung. Sebab kita memang dilibatkan, melalui proses pemilihan demokratis yang disepakati untuk menentukan siapa saja yang mewakili kepentingan masing-masing dalam suatu tatanan yang disebut negara. Agar semua hidup berdampingan, rukun dan damai satu dengan lainnya menjadi suatu bangsa.
Kita pula yang memilih pasangan yang akan memimpin wilayah. Mulai dari satuan terkecil dimana kita terdaftar, yakni kepala daerah kabupaten atau kota, gubernur untuk lingkup provinsi, lalu presiden sebagai pemimpin tertinggi bagi seluruh Nusantara.
Politikus
Politikus sesungguhnya memang penjaja gagasan, janji-janji, juga harapan. Serupa dengan agen penjualan obat, klub wisata dan sepeda motor, atau produk maupun jasa yang lain.
Kitalah konsumen potensialnya bagi gagasan, janji, maupun harapan yang mereka perdagangkan. Agar melegitimasi kerja maupun penganggarannya untuk direalisasikan. Tentu saja menggunakan kekayaan kita, Tanah air Indonesia beserta segala hasil dan daya gunanya.
Tapi sesungguhnya, mereka tak memiliki keharusan menjamin hasil yang persis sama. Dengan janji maupun harapan, baik yang tersurat apalagi tersirat. Dari gagasan-gagasan yang sebelumnya ditawarkan.
Kewajiban mereka hanya memastikan bahwa segala sesuatu yang dilakukannya, sesuai dengan kebijakan dan tata cara baku yang telah disepakati. Tak melanggar atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Termasuk tak melakukan praktik-praktik yang merugikan negara, dalam makna administratif.
Bukan soal hasil maupun manfaat. Dalam hal itu, segalanya selalu lentur.
Sebab, sebenarnya tak ada layanan kepuasan pelanggan politik yang berlaku umum. Sehingga mereka dapat menagih harapan maupun janji sebagaimana yang ditawarkan. Apalagi menuntut kompensasi dan ganti rugi.
Demokrasi
Demokrasi sejatinya meniadakan monopoli. Hal yang memungkinkan berlangsungnya persaingan yang sehat antar mereka yang ingin merebut simpati untuk memperoleh suara pemilih yang terbanyak. Sehingga kemudian berhak untuk mewakili, juga memutuskan atas nama semua.
Demokrasi sejatinya kesempatan, bagi masing-masing pihak untuk membuktikan kebenaran janji maupun harapan dari gagasan-gagasan yang semula dijajakan.
Demokrasi sejatinya peluang, bagi mereka yang terpilih untuk membuktikan seberapa jitu mimpi-mimpinya, juga tentang kepiawaian mewujudkan janji dan harapan yang menyertai.
Demokrasi juga membuka jalan, agar yang tersisih bisa melakukan introspeksi sambil menyempurnakan gagasan yang sebelumnya kalah bersaing untuk kembali ditawarkan, saat nanti kesempatan kontestasi terbuka lagi.
Maka demokrasi bukanlah kartel, atau kongsi antar pihak yang sebelumnya begitu sengit berseteru dan saling meniadakan. Sehingga masyarakat konsumennya terpecah-belah.
Demokrasi yang kita pilih hari ini, sejatinya bukan penawar bagi kepentingan sempit oknum maupun kelompok tertentu. Tapi justru didasari iktikad bersama untuk mempersembahkan yang terbaik bagi bangsa dan negara.
Bhineka Tunggal Ika
Sesungguhnya para pendiri bangsa ini telah sempurna merumuskan konsep demokrasi yang paling sesuai dengan karakter budaya dan prinsip kebangsaan kita, yang berbeda-beda tapi satu. Bhinneka Tunggal Ika.
Musyawarah dan mufakat telah dicanangkan sebagai salah satu dari 5 dasar mengapa kita bernegara. Jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan.
Bangsa yang besar ini, memang dibangun dari kekayaan budaya dan adat-istiadat yang unik, juga beragam. Kebersamaan dan gotong royong adalah segalanya. Bukan tirani mayoritas, maupun diktator mayoritas.

Menyatukan perbedaan membutuhkan kesabaran dan jatuh-bangun. Membangun kebersamaan memerlukan keuletan, agar masing-masing tumbuh rasa percaya dirinya, terbina secara berkesinambungan di atas luka dan pengorbanan.
Pada kesabaran dan keuletan itulah tantangan bermula. Ketika laku budaya korupsi, kolusi dan nepotisme bertemu inangnya. Hal yang kemudian menjadi virus yang sangat mematikan.
Untuk menyatukan perbedaan dan membangun kebersamaan yang sesungguhnya niscaya itu.
Tanpa “check and balance”
Setelah berjalan 32 tahun bersama pemerintahan Suharto dan rezim Orde Barunya, kita berkesimpulan musyawarah dan mufakat hanyalah omong kosong tanpa “check and balance“.
Kita lalu sepakat membongkarnya, mereformasi peran dan fungsi setiap penopang kehidupan berbangsa dan bernegara, agar “lebih” demokratis.
Tapi kita lupa, tentang bagaimana proses peralihannya. Soal transformasi kehidupan bangsa yang serba majemuk ini dari budaya “musyawarah-mufakat” yang sebelumnya kepada “one man one vote” yang baru.
Kita lalai, kesan maupun pengalaman sebelumnya –tentang “musyawarah-mufakat” yang keliru dan jauh melenceng dari hakikat sejatinya– telah merasuki kehidupan sebagian besar bangsa ini.

Baca Juga: Pemilu Era Jokowi Lebih Buruk dari Pemilu Masa Orde Baru?
Kita frustasi, jejak adat-istiadat keliru tentang musyawarah-mufakat itu, telah begitu digdaya untuk menafikan segala tekad yang dicanangkan saat ingin mereformasi diri, tahun 1998 lalu.
Kita tak sanggup menghadapi kenyataan, musyawarah-mufakat yang semula dirumuskan sebagai penawar keberagaman justru berubah menjadi ancaman yang mematikan bangsa yang ingin bertobat ini.
Kita malah jemu menggerutu ketika KPK membukukan jumlah tangkapan secara eksponensial. Sebaliknya malah menuding lembaga yang kita lahirkan bersama gerakan reformasi untuk memberantas korupsi yang sudah mendarah daging itu sebagai biang kerok kegagalan membuktikan janji dan mewujudkan harapan. Pada gagasan-gagasan ganjil, mentah dan penuh kemunafikan.
Menyakitkan
Saya tak paham. Jika hanya berkeinginan menghidupkan kembali musyawarah mufakat yang pernah konyol itu, untuk apa semua pengorbanan yang kita lakukan selama ini?
Konsumen politik Indonesia hari ini, memang tak berhak menuntut kembali ongkos yang telah dibayarnya.
Tapi ingatlah pesan ini.
Masa depan kemajuan teknologi akan membalas kalian, para penguasa yang hari ini menyalahgunakan peran dan fungsi politik, dengan cara yang amat menyakitkan dan tak terlupakan. Mungkin hingga ke anak-cucumu.
22 Oktober 2019
BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini