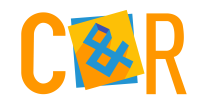Ceknricek.com — Di Indonesia, sejarah jalan tol bermula karena kondisi yang memaksa. Ketika harga minyak dunia melorot sehingga penerimaan negara terganggu. Padahal kita sedang memiliki banyak kebutuhan. Termasuk mencicil hutang untuk membiayai pembangunan yang kemudian menjadi jalan tol pertama itu (Jagorawi).
Sebetulnya, pada masa tersebut, negara tetangga Malaysia, sudah lebih dulu membangun dan mengoperasikan jaringan jalan bebas hambatan yang disebut ‘highway’. Mereka setidaknya memberi kemudahan para pengendara sejak menyeberang dari Penang, menuju Kualalumpur, dilanjutkan ke Johor, hingga menyeberang lagi ke negara tetangganya, Singapura. Suharto dan pemerintahan Orde Baru tentu tak ingin ketinggalan. Lalu menggagas ‘highway’ yang menghubungkan Jakarta dengan kota Bogor dan Ciawi.
Perkeliruan #1
Pertama-tama soal pemilihan ruas Jakarta-Bogor-Ciawi itu sendiri. Hal tersebut sebetulnya bertentangan dengan kebijakan strategis tata ruang regional. Perkembangan ke arah selatan ibukota, justru ingin dihindari. Sebab kawasan tersebut merupakan daerah tangkapan air yang perlu dijaga. Agar tak mengirim banjir ke Jakarta yang berada di hilirnya. Apalagi ketika musim hujan tiba.
Keberadaan jalan bebas hambatan Jagorawi, malah semakin memudahkan akses kawasan tersebut, ke dan dari Jakarta. Selain ke Istana Bogor, para pegawai instansi-instansi pemerintah yang memiliki mes maupun fasilitas pertemuan dinas di sana, tentu saja turut diuntungkan. Sudah menjadi rahasia umum pula, jika banyak di antara para pejabat yang memiliki vila dan rumah peristirahatan mewah di wilayah yang sejuk itu. Persoalsn klasik yang hingga hari ini selalu menjadi isu nasional. Pada masa tersebut, kawasan Puncak memang menjadi salah satu tujuan wisata favorit warga Jakarta.
Jalan tol Jagorawi juga memangkas waktu perjalanan Jakarta-Bandung yang pada akhir tahun 1970-an itu, merupakan lalu lintas antar kota terpadat dari dan ke Jakarta.
Mengacu straregi tataruang regional yang telah disampaikan sebelumnya, prioritas pengembangan infrastruktur transportasi saat itu, mestinya tak di arahkan ke sana. Melainkan ke arah barat (koridor Tangerang-Balaraja) atau timur (koridor Bekasi-Karawang).
Perkeliruan #2
Setelah penerimaan negara terganggu akibat harga minyak dunia yang sedang merosot tajam, berkembanglah gagasan untuk melibatkan ‘partisipasi masyarakat’. Pengguna jalan bebas hambatan tersebut, wajib membayar berdasarkan tarif yang dikenakan. Tentunya jika mereka ingin berkendara di sana. Bagi yang tak berkenan, pilihannya harus melintas di jalan alternatif lain yang tersedia. Yakni Raya Bogor dan Parung.
‘Terobosan’ itu, kemudian menjadi preseden bagi bisnis jalan tol di Tanah Air. Perkeliruan yang kemudian justru menginspirasi putri tertua Suharto, Siti Hardianti Rukmana, mengembangkan PT Citra Marga Nusa Pala sebagai pioneer investasi jalan tol di Indonesia (pada ruas Cawang-Priok yang terintegrasi sebagai bagian Jakarta Intra Urban Tollroad yang membentang hingga Grogol).
Saat itu, ketika proses pengalihan Jagorawi sebagai jalan tol sedang berlangsung, sebetulnya banyak pandangan mengemuka yang mempertanyakan konstitusionalitas gagasan tersebut. Sebab, jalan raya termasuk hal strategis yang harus disediakan dan dikuasai Negara. Wacana yang mengkhawatirkannya sebagai titik masuk kapitalisme pada hajat hidup masyarakat luas, kemudian mengemuka. Meski mulanya negara melimpahkan kepada perseroan terbatas Jasa Marga. Badan usaha yang dimiliki Negara.
Lalu, pemerintahan Suharto yang saat itu berkuasa, menjelaskan. Bahwa kebijakan tersebut hanya sementara waktu. Jasa Marga, sesuai kesepakatan wewenang pengelolaan yang diberikan, wajib menyerahkan kembali kepada Negara. Yakni setelah 25 tahun mengoperasikannya.
Selain Jagorawi, hak pengelolaan infrastruktur lain yang waktu itu dibiayai Negara — Jembatan Tol Rajamandala yang melintasi Citarum di kawasan Cianjur — pengelolaannya juga diserahkan kepada Jasa Marga.
Untuk yang satu ini, kemudian hari memang diserahkan kembali kepada negara. Kini penggunanya tak lagi dikenakan biaya ketika melintas di sana.
Perkeliruan #3
Perkeliruan demi perkeliruan tersebut, kemudian bersahut-sahutan dengan kebutuhan dan rencana investasi untuk menopang pembangunan. Saat itu, Jepang merencanakan relokasi sejumlah industri manufakturnya ke negeri kita. Agar produk-produk mereka dapat bersaing di pasar global. Biaya tenaga kerja di negeri mereka memang semakin tinggi.
Infrastruktur untuk menopang industri yang terbaik saat itu, memang terkonsentrasi di seputar ibukota. Mulai dari pembangkit listrik (Jatilihur), bandara internasional, pelabuhan laut, hingga jaringan jalan raya. Pusat kekuasaan pun berada di sana. Maka peluang relokasi tersebut kemudian diarahkan ke koridor barat (Tangerang-Merak) dan timur (Bekasi-Cikampek) ibukota. Mengorbankan lahan-lahan pertanian subur yang ada di sana.
Tapi prasarana transportasi yang ada untuk memudahkan lalu lintas bahan baku industri, maupun kegiatan ekspor dan distribusi hasil produksi pabrik-pabrik yang akan berkembang di sana, dianggap tak memadai. Apalagi untuk mengantisipasi peningkatan volume lalu lintas setelah aktivitas industrinya berjalan.
Maka sejak saat itu, bisnis jalan tol di Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Narasi tanggung jawab Negara untuk ‘menjamin kemudahan’ mobilitas masyarakat, orang maupun barangnya, kemudian bergeser. Bahkan berubah. Dari ‘menjamin kemudahan’ menjadi sekedar ‘memudahkan’. Artinya, untuk menunaikan kewajiban tersebut, Negara ‘boleh’ — bahkan kemudian dianggap ‘perlu’ — melibatkan modal swasta.
Kekhawatiran bergesernya paradigma jalan tol sebagai lahan kapitalisme, akhirnya memang sungguh-sungguh mewujud. Suharto kemudian ‘terpaksa’ mengikhlaskan berbagai perusahaan swasta, mengambil bagian pada ruas-ruas jalan tol lain yang dikembangkan. Bangun Cipta Sarana milik Siswono Yudohusodo mengambil bagian Jakarta Cikampek. Sementara salah satu perusahaan milik Hutomo Mandala Putra pada ruas Jakarta-Merak.
Konsesi sebagian besar ruas-ruas jalan tol lainpun, juga dikuasai sejumlah perusahaan raksasa dan pemodal kuat di Tanah Air. Meski pekerjaan konstruksinya tak kunjung dilaksanakan hingga era Suharto dan pemerintahan Orde Baru-nya berakhir.
Perkeliruan #4
Peran modal swasta dalam pembangunan, tentu saja diperlukan. Hal tersebut memang merupakan bagian dari konsepsi partisipasi masyarakat. Meski demikian, sepatutnya pula disikapi secara matang dan hati-hati. Sebab, antara ‘partisipasi’ dsn ‘investasi’, terdapat perbedaan yang amat tipis. Tapi sesungguhnya berimplikasi sangat mendasar dalam hal memaknainya. Jika ‘partisipasi’ maksudnya lebih ditujukan pada tataran publik dan kepentingan (masyarakat) lebih luas, ‘investasi’ justru cenderung bersifat sangat privat dan demi kepentingan finansial semata. Bagi yang terakhir, ‘tak pernah ada makan siang yang gratis.’
Pergeseran peran dan tanggung jawab Negara, dari ‘menjamin kemudahan (bagi kepentingan mssyarakat)’ menjadi ‘kemudahan (partisipasi swasta berinvestasi)’ itu, kemudian justru semakin dirayakan oleh pemerintah berkuasa secara berlebihan. Terutama pada era Presiden Joko Widodo.
Pada mula kepemimpinannya, kita disodorkan kebijakan populis yang mengundang simpati. Suatu ‘kebetulan’ yang memanfaatkan anggaran subsidi BBM yang diwariskan SBY. Ketika itu, harga minyak dunia merosot tajam sehingga alokasinya tak termanfaatkan. Joko Widodo kemudian memanfaatkannya sebagai ‘modal’ untuk mendeklarasikan program pembangunan infrastrukturnya.
Banyak kalangan yang sudah mengingatkan. Suatu proyek jangka panjang akan sangat riskan jika hanya mengandalkan anggaran subsidi yang tak termanfaatkan pada tahun awal pemerintahannya itu. Apalagi tanpa disertai pembenahan dan pengembangan struktur penerimaan yang tak mencerminkan ketahanan jangka panjang. Sementara harga minyak sendiri tetap berkemungkinan untuk bergejolak lagi. Hal yang pada akhirnya menyebabkan negara kembali terdesak. Setidaknya dalam hal melakukan kebijakan yang dapat menstabilkan harga eceran BBM.
Kita tentu mudah menelesurinya kembali ke sejumlah peristiwa yang berlangsung beberapa tahun lalu. Salah satu, saat Ignatius Jonan perlu mengoreksi pengumuman kenaikan BBM yang disampaikannya menjelang pertemuan internasional di Bali waktu itu. Tekanan neraca pembiayaan negara maupun Pertamina, akibat lonjakan harga minyak dunia, menyebabkan kenaikan harga BBM dipandang sebagai hal yang tak terelakkan. Jonan mengumumkan kenaikan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Menteri ESDM. Tapi kemudian Joko Widodo tak menyetujui. Sehingga Jonan harus menjilat kembali pengumuman yang disampaikan beberapa jam sebelumnya.
Tekanan pada aliran kas perusahaan-perusahaan BUMN yang diserahi tugas membangun (sekaligus menalangi pembiayaan) proyek-proyek infrastruktur, sesungguhnya sudah terlihat jauh hari sebelumnya. Hal yang mudah dicermati dari lonjakan hutang Negara yang rasionya sangat tak sepadan dengan pertumbuhan penerimaan. Terutama yang merupakan bagian kewajiban jangka pendeknya.
Perkeliruan #5
Tekanan hutang dan kewajiban yang jatuh tempo, mendesak pemerintah untuk menyegerakan rencana pendirian lembaga untuk menarik investasi asing (Lembaga Pengelola Investasi, LPI). Dari Rp 75 triliun modal Indonesia, hingga 2021 ini akan disuntikkan Rp 30 triliun (Rp 15 triliun sudah disetor tahun lalu, dan Rp 15 triliun lagi dianggarkan tahun ini). Pemerintah akan menggenapi kekurangannya dengan menyertakan asset-asset yang dikuasai. Di antaranya adalah kepemilikan sejumlah jalan tol yang selama ini ditugaskan kepada sejumlah BUMN karya.
Melalui LPI tersebut, pemerintah mengharapkan akan menarik investasi asing. Amerika dan Jepang pernah dikabarkan akan menyuntikkan sekitar Rp 84 triliun. Melalui lembaga yang didirikan setelah UU Cipta Kerja No 11/2020 disahkan itu, pemerintah tentu berharap dapat menarik penyertaan asing lebih banyak dan lebih luas lagi.
Langkah ini tentu akan menghantarkan kita pada perkeliruan yang lebih dalam. Sebab, sebagaimana dijelaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Komisi X DPR sekitar seminggu yang lalu, LPI sejatinya memiliki 3 fase transaksi: investasi, kepemilikan, dan exit. Ketiganya tentu dikaji berdasarkan ‘financial return’, ‘business valuation’, dan ‘market share’. Bukan ‘equality’, ‘social welfare distribution’, ‘GINI ratio’, atau ‘human capital index’.
Perkeliruan #6
Jalan tol yang awalnya dimaklumi sebagai ‘kompensasi darurat’ ketidakmampuan negara menyediakan prasarana dan sarana memadai, untuk melayani mobilitas masyarakatnya (orang maupun barang), malah bergeser menjadi satu-satunya pilihan yang diharapkan menyediakan standar pelayanan. Makna bebas hambatan yang disandangnya, kemudian diterjemahkan ke dalam sejumlah ketentuan teknis. Seperti kecepatan minimum rata-rata, jumlah lajur, pemisahan arah, persilangan sebidang, hingga jarak antar simpang susun, akses masuk maupun keluarnya. Semua hal tersebut bahkan telah tersusun dalam sejumlah ketentuan yang berkekuatan hukum.
Tapi pernahkah negara memperdulikan tingkat pelayanan minimum yang telah memiliki dasar hukum itu, untuk dipenuhi penyelenggara jalan tol yang dikuasakannya?
Sebelum pandemi sekarang ini, sudah menjadi pemahaman umum jika pada hari dan jam tertentu, kemacetan dan antrian panjang pada ruas-ruas jalan tol, merupakan fenomena yang biasa dihadapi penggunanya. Perkeliruan di tingkat ini bahkan semakin nyata menampilkan kesemena-menaan kekuasaan. Hak dan kepentingan masyarakat pengguna yang telah membayar tarif pelayanan yang dijanjikan, disepelekan begitu saja. Demi kepentingan investasi.
Mengapa demikian?
Alih-alih mengembangkan akuntabilitas pelayanan (misalnya dalam memenuhi janji waktu tempuh minimal), upaya yang diutamakan pemerintah justru pada maksimalisasi pendapatan usaha yang dilakukan investor. Hal ini terlihat dari rencana penerapan sistem pembayaran tanpa sentuh yang memungkinkan kendaraan tak perlu menghentikan atau memperlambat lajunya. Metode ini, memang akan mampu mengurangi antrian dan kemacetan di pintu-pintu tol. Dengan demikian, kapasitas tampung jalan tol tentu dapat dimaksimalkan. Hal yang pada gilirannya akan berdampak pada pengembalian investasi.
Tapi bagaimana soal standar pelayanan konsumen yang telah dilindungi undang-undang.
Ilustrasi yang lebih sederhana, apakah pengguna tetap membayar tarif yang sama dengan yang ditetapkan, jika ternyata harus melintasi ruas jalan tol yang digunakan hanya dengan kecepatan 30 km/jam, misalnya?
Atau, apa kompensasi pengguna ketika sebagian badan jalan sedang diperbaiki sehingga harus terjebak dalam antrian panjang?
Atau, bagaimana tanggung jawab pengelola jalan tol terhadap kerusakan kendaraan akibat permukaan jalan yang rusak?
Atau, apa dasar pembenaran atas gangguan kenyamanan yang disebabkan kendaraan-kendaraan dengan pengawalan khusus yang ingin diistimewakan? Siapa saja sebetulnya yang perlu dan boleh dikecualikan?
Perkeliruan #7
Ketika pelanggan yang sudah berkorban dengan membayar sejumlah biaya demi mendapat pelayanan ‘bebas hambatan’ yang dijanjikan saja, begitu mudah diabaikan, bagaimana kira-kira kepedulian pemerintah yang sejatinya mewakili negara, terhadap daya dukung dan kapasitas ruang di mana ruas jalan tol dibangun?
Ruas tol Cipali yang amblas kemarin, telah gamblang menjelaskan. Perkeliruan demi perkeliruan yang dijelaskan di atas, semakin menegaskan ‘pengkhianatan’ yang dilakukan terhadap amanah konstitusi terhadap rakyatnya. Alih-alih memudahkan dan meningkatkan kesejahteraan, pemerintah yang berkuasa justru semakin menegaskan kesemena-menaannya.
Dengan kekuasaan yang dimiliki, prinsip dan hakekat Planologi dapat saja disangkal maupun diabaikan. Tapi alam semesta tak mungkin dibohongi dan diam saja. Ruas jalan tol yang amblas di Cipali, longsor di Sumedang, banjir di Kalimantan, dan seterusnya, telah membuktikannya.
Ke depan, tentu kita akan menyaksikan — bahkan mungkin mengalami — yang lebih banyak lagi.
Mardhani, Jilal — 12 Februari 2021